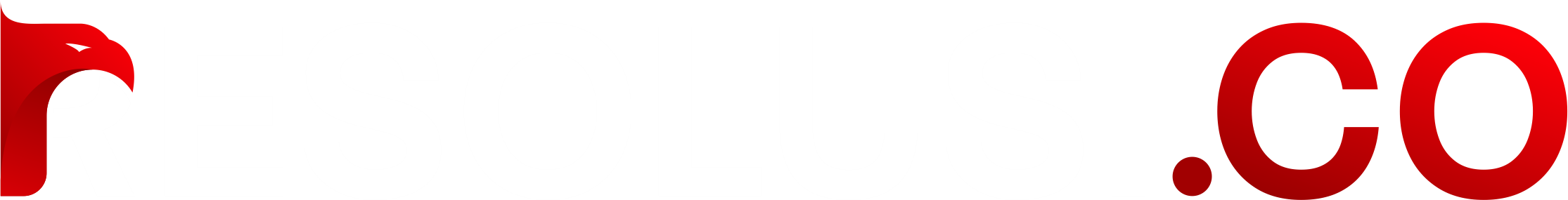COUNTDOWN KE KRISIS: Mengapa Kekerasan dalam Rumah Tangga Melonjak Pasca Perayaan Tahun Baru?

- Perayaan Tahun Baru justru menjadi periode paling berbahaya bagi perempuan dan anak, dengan lonjakan signifikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berulang setiap Januari, baik di Indonesia maupun secara global.
- Tekanan finansial, ekspektasi sosial yang tidak realistis, kelelahan emosional, dan kontak intens dengan pelaku menciptakan “badai sempurna” kekerasan, yang diperparah oleh budaya patriarki dan lemahnya perlindungan sistem hukum.
- Sebagian besar korban terjebak dalam siklus ketakutan dan ketergantungan, sementara negara dan sistem dukungan belum hadir secara memadai, terutama di masa liburan ketika korban paling membutuhkan perlindungan.
 , PAMEKASAN – Saat jam menunjuk pukul 00.00 pada 1 Januari 2026 nanti, jutaan orang Indonesia akan merayakan pergantian tahun dengan suka cita. Namun, bagi ribuan perempuan dan anak-anak, detik-detik itu bukan menandai harapan baru, melainkan awal dari mimpi buruk yang berulang.
, PAMEKASAN – Saat jam menunjuk pukul 00.00 pada 1 Januari 2026 nanti, jutaan orang Indonesia akan merayakan pergantian tahun dengan suka cita. Namun, bagi ribuan perempuan dan anak-anak, detik-detik itu bukan menandai harapan baru, melainkan awal dari mimpi buruk yang berulang.
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena mengkhawatirkan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 1.010 kasus dan menempati urutan pertama korban paling banyak yang melaporkan. Angka ini hanya puncak gunung es dari realitas yang jauh lebih kelam.
Statistik yang Membisu
Sepanjang 2024, Indonesia mencatat 28.789 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari total tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. KDRT menjadi jenis kasus kekerasan tertinggi dengan 19.045 kasus dilaporkan, angka yang meningkat drastis 56 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 18.466 kasus.
Namun, yang jarang dibahas adalah pola temporal yang mengejutkan: lonjakan kasus KDRT secara konsisten terjadi pasca perayaan hari besar, terutama tahun baru.
Data dari Polres Trenggalek mencatat lonjakan dramatis. Kasus kriminal meningkat 28,3 persen pada 2025, dengan KDRT dan pengeroyokan mendominasi laporan. Di Kuningan, Jawa Barat, kasus KDRT meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 9 kasus di 2024 menjadi 23 kasus di 2025.
Kota Samarinda mencatat 294 kasus kekerasan dengan 303 korban ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sepanjang 2025. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Rilis Akhir Tahun 2024 menegaskan bahwa KDRT adalah jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun mencapai 11.098 perkara.
Angka-angka itu, betapapun mengejutkan, masih jauh dari realitas. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender pada 2024, naik 14,17 persen dari tahun sebelumnya. Namun, aktivis dan akademisi memperkirakan kasus yang tidak dilaporkan bisa mencapai lima hingga sepuluh kali lipat.
“Mayoritas korban KDRT tidak pernah melapor,” ungkap Dian Ekawati, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Kemen PPPA. “Mereka hidup dalam siklus ketakutan. Ingin keluar, tapi tidak tahu harus kemana atau takut tidak dipercaya. Ini yang memicu psikologis korban makin turun.”
Anatomi Lonjakan Pasca Tahun Baru
Penelitian global mengonfirmasi pola yang sama di berbagai negara. Studi yang dipublikasikan dalam Emergency Radiology oleh Dr. Bharti Khurana dari Brigham’s Trauma Imaging Research and Innovation Center menganalisis data nasional AS dari 2005-2017.
Temuan mereka mengejutkan: malam Tahun Baru mencatat tingkat kekerasan pasangan tertinggi dibandingkan hari-hari lain sepanjang tahun, bahkan melampaui hari libur besar lainnya seperti St. Patrick’s Day, Hari Kemerdekaan, atau Thanksgiving.
“Kami memiliki bukti yang kuat karena ini adalah studi nasional,” kata Dr. Khurana. “Natal dan Malam Tahun Baru lebih umum untuk kekerasan pasangan intim. Jika saya melihat cedera lebih sering pada hari-hari ini, saya tahu kemungkinan besar itu adalah kekerasan domestik.”
Di Australia, data kriminal menunjukkan insiden keluarga cenderung lebih sering terjadi pada Desember dan Januari dibandingkan bulan-bulan lainnya. Polisi Australia Barat melaporkan peningkatan rata-rata harian laporan kekerasan keluarga sebesar 24,2 persen selama periode Natal hingga Tahun Baru.
Queensland Police mencatat lonjakan yang lebih dramatis: peningkatan 32 persen panggilan terkait kekerasan keluarga dan domestik selama periode Natal hingga Tahun Baru dibandingkan tahun sebelumnya. Di Victoria, jumlah rata-rata insiden kekerasan keluarga yang tercatat naik 33 persen hanya pada Hari Natal.
Di Inggris, panggilan ke saluran bantuan kekerasan domestik nasional naik 66 persen pada Desember. Satu survei menemukan empat dari sepuluh orang yang disurvei takut periode Natal akan menyebabkan berakhirnya pernikahan mereka.
Indonesia tidak terkecuali dari pola global ini. Meski data spesifik tentang lonjakan pasca-tahun baru belum terpublikasi secara luas, laporan dari Unit PPA di berbagai daerah mengonfirmasi peningkatan signifikan kasus KDRT yang dilaporkan pada Januari-Februari setiap tahunnya.
Faktor Pemicu yang Saling Menguat
Apa yang membuat periode perayaan tahun baru menjadi momen paling berbahaya bagi korban kekerasan domestik? Penelitian mengidentifikasi setidaknya lima faktor utama yang saling menguatkan.
Pertama, tekanan finansial. Survei terbaru menemukan lebih dari 50 persen orang Australia kesulitan membeli hadiah untuk acara spesial seperti Natal. Di tengah krisis biaya hidup saat ini, banyak orang mengalami tekanan finansial yang menurut penelitian terkait dengan tindakan kekerasan pasangan.
Di Indonesia, fenomena ini bahkan lebih akut. “Tuntutan sosial untuk merayakan tahun baru dengan ‘layak’ menciptakan beban finansial yang luar biasa,” jelas psikolog klinis Nadya Pramesrani. “Bagi keluarga dengan ekonomi lemah, ini menjadi sumber stres yang sangat berat. Pelaku KDRT sering mengalihkan frustrasi ekonomi mereka ke pasangan atau anak-anak.”
Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Interpersonal Violence menemukan bahwa stres finansial meningkatkan risiko kekerasan pasangan hingga tiga kali lipat. Ketidakmampuan memenuhi ekspektasi sosial selama perayaan menciptakan rasa malu dan kegagalan yang memicu kemarahan.
Kedua, konsumsi alkohol yang meningkat. Musim liburan sering dikaitkan dengan peningkatan konsumsi alkohol. Menurut Bureau of Crime Statistics and Research New South Wales, sekitar seperempat kekerasan domestik dari Juli 2023 hingga Juni 2024 terkait alkohol.
“Tidak semua orang yang minum alkohol akan menjadi kekerasan,” jelas peneliti dari University of Nevada, Reno. “Namun, alkohol mengubah cara otak berfungsi dengan mengurangi kemampuan kita mengontrol impuls, yang dapat meningkatkan kemungkinan menjadi kekerasan ketika diprovokasi.”
Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Addiction menganalisis hubungan harian antara konsumsi alkohol dan kekerasan pasangan pada orang dewasa muda. Temuan menunjukkan korelasi kuat: hari-hari dengan konsumsi alkohol lebih tinggi secara signifikan terkait dengan peningkatan insiden kekerasan.
Di Indonesia, meski konsumsi alkohol bukan norma sosial dominan, fenomena serupa terjadi dengan bentuk lain. “Tekanan emosional yang tidak terkelola dengan baik, dikombinasi dengan kelelahan fisik akibat perayaan, menciptakan kondisi serupa,” ungkap Ayunda Rahmadani, psikolog Universitas Mulawarman yang juga Koordinator Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda.
Ketiga, ekspektasi sosial yang tak terpenuhi. Musim liburan datang dengan ekspektasi tinggi, baik sosial maupun personal. Banyak orang merasakan tekanan untuk memenuhi kewajiban sosial: membeli hadiah mahal, menyiapkan makanan mewah, dan berbagai “keharusan” lainnya untuk menciptakan liburan yang “sempurna”.
“Ekspektasi ini menciptakan standar yang tidak realistis,” jelas Joy Walker-Jones, LCSW dari UCSF Women’s Specialty Program. “Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti hidangan tidak sempurna, hadiah tidak cukup mewah, atau acara keluarga penuh konflik, kekecewaan dan frustrasi dapat memicu agresi pada individu yang sudah rentan terhadap perilaku kekerasan.”
Tekanan untuk mempertahankan “wajah bahagia” selama periode yang seharusnya menyenangkan membuat banyak korban merasa terisolasi dan malu. “Masyarakat mengharapkan semua orang bahagia saat perayaan,” kata Desy Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA. “Ketika rumah Anda penuh kekerasan, tetapi Anda harus pura-pura bahagia, itu menciptakan beban psikologis yang luar biasa.”
Keempat, kontak yang diperpanjang dan isolasi. Liburan sering melibatkan waktu yang diperpanjang bersama keluarga dan teman. Bagi korban KDRT, ini berarti lebih banyak waktu terpapar pada pelaku dengan lebih sedikit kesempatan untuk melarikan diri atau mencari bantuan.
“Korban menjadi lebih rentan terhadap kekerasan karena kontak yang berkepanjangan atau meningkat dengan keluarga dan teman,” jelas Dr. Khurana. “Pelaku sering memanfaatkan keadaan ini untuk memperkuat kontrol mereka terhadap korban.”
Paradoksnya, meski dikelilingi orang, korban justru sering merasa lebih terisolasi. “Kebanyakan teman dan dukungan sosial korban sibuk dengan perayaan keluarga mereka sendiri,” ungkap terapis yang mengkhususkan diri pada kekerasan pasangan. “Tekanan untuk bersama keluarga selama ini dapat mencegah mereka mencari bantuan.”
Penelitian menunjukkan bahwa isolasi fisik juga meningkat selama liburan. Banyak pusat layanan kesehatan dan layanan dukungan lainnya tutup atau beroperasi dengan jam terbatas, yang membatasi kemampuan korban untuk mencari bantuan saat dibutuhkan.
Kelima, suhu dan lingkungan. Faktor yang jarang dibahas: musim liburan di belahan selatan, termasuk Australia, bertepatan dengan suhu musim panas yang meningkat. Penelitian menunjukkan suhu yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan kekerasan.
“Peneliti menduga asosiasi ini mungkin karena peningkatan ketidaknyamanan dan frustrasi, serta acara sosial yang lebih sering di mana konflik dapat muncul,” jelas akademisi dari The Conversation.
Di Indonesia, meski tidak mengalami musim panas ekstrem, pergantian tahun terjadi di puncak musim hujan, periode yang juga menciptakan tekanan tersendiri. “Hujan deras, banjir, dan gangguan aktivitas sehari-hari menambah stres pada keluarga yang sudah rentan,” kata Ibnu Araby, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
Korban yang Terjebak
Rina (bukan nama sebenarnya), 34 tahun, telah mengalami kekerasan dari suaminya selama delapan tahun. Namun, Januari selalu menjadi bulan terburuk.
“Setiap tahun sama,” katanya dengan suara pelan dalam wawancara di shelter perempuan korban kekerasan di Jakarta Selatan. “Menjelang tahun baru, dia stres karena harus beri angpao ke saudara, traktir teman-temannya, bayar ini-itu. Uangnya habis. Dia mulai marah-marah. Salahkan saya karena ‘terlalu boros’, padahal saya cuma beli kebutuhan dasar anak-anak.”
“Tanggal 1 Januari, dia bangun dengan mood buruk. Lihat rumah berantakan habis acara tadi malam. Mulai bentak-bentak. Kalau saya jawab sedikit atau diam saja, dia pukul. Tahun ini parah. Sampai gigi saya copot.”
Rina baru melapor ke polisi setelah delapan tahun. “Saya pikir, kalau saya sabar, nanti dia berubah. Apalagi Tahun Baru kan harusnya resolusi baru, kehidupan baru. Tapi nggak. Malah makin parah setiap tahun.”
Kisah Rina bukan pengecualian. Menurut data UPTD PPA Samarinda, mayoritas korban yang akhirnya melapor telah mengalami kekerasan selama bertahun-tahun—rata-rata tiga hingga lima tahun—sebelum berani mencari bantuan.
“Banyak perempuan yang hidup dalam siklus ketakutan,” kata Dian Ekawati dari Kemen PPPA. “Mereka ingin keluar, tetapi tidak tahu harus kemana atau takut tidak dipercaya.”
Budaya Patriarki yang Melanggengkan
Di balik statistik dan kasus individual, terdapat struktur sosial yang melanggengkan kekerasan: budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia.
“Dalam masyarakat patriarki, laki-laki sering kali diposisikan sebagai pihak superior, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah,” jelas analis Badan Keahlian DPR RI dalam kajian yang dipublikasikan Januari 2025. “Kondisi ini menciptakan ketidakadilan gender yang menormalisasi kekerasan karena laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar dalam menentukan aturan rumah tangga.”
Normalisasi kekerasan ini terlihat jelas dalam bahasa sehari-hari. Ungkapan seperti “laki-laki boleh marah”, “istri harus nurut suami”, atau “urusan rumah tangga jangan dibawa ke luar” adalah manifestasi dari struktur patriarki yang melindungi pelaku dan membungkam korban.
“Dengan ketidakberdayaan posisi perempuan dalam budaya patriarki, maka secara tidak langsung akan memengaruhi pelaporan, penanganan, serta pemulihan korban KDRT,” lanjut analis tersebut. “Korban menjadi takut dan enggan untuk melapor sehingga kasus KDRT akan terus terulang.”
Fenomena ini diperparah oleh ketergantungan ekonomi. Penelitian menunjukkan sebagian besar korban KDRT tidak memiliki kemandirian finansial karena suami menguasai keuangan keluarga. “Kekerasan ekonomi adalah bentuk KDRT yang sering tidak dikenali tapi sangat melumpuhkan,” ungkap Ayunda Rahmadani.
Sistem Hukum yang Belum Efektif
Indonesia telah memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, dalam implementasi di lapangan, aturan tersebut belum sepenuhnya efektif melindungi korban.
“Masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait UU PKDRT, dan belum adanya restitusi bagi korban menjadi beberapa kendala pelindungan korban KDRT,” ungkap kajian DPR RI.
Kasus di Kulonprogo pada 2023 menjadi ilustrasi pahit. Seorang dokter gigi berinisial TA menjadi korban kekerasan suaminya. Meski bukti medis jelas menunjukkan kekerasan fisik berat, jaksa hanya menuntut hukuman 6 bulan penjara, sebuah tuntutan yang dikritik keras oleh keluarga korban dan aktivis hukum sebagai “tidak mencerminkan keseriusan kejahatan”.
“Rendahnya tuntutan ini dinilai merugikan korban dan memberikan pesan bahwa KDRT bukan kejahatan serius,” kata pengacara yang menangani kasus tersebut.
Data menunjukkan banyak kasus yang telah dilaporkan bahkan sudah ditangani oleh pihak berwenang sering dihentikan atau dicabut oleh pihak terkait. “Ini bukan karena korban memaafkan pelaku,” jelas aktivis perempuan yang meminta anonim. “Tapi karena tekanan sosial, ekonomi, dan ketidakpercayaan pada sistem hukum yang tidak melindungi mereka.”
Dampak pada Anak yang Terlupakan
Korban KDRT bukan hanya pasangan yang mengalami kekerasan langsung. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan orang tua mereka adalah korban yang sering terlupakan.
“Tahun 2020 melihat peningkatan kekerasan domestik, tanpa dukungan, trauma menyaksikan atau mengalami kekerasan dapat tinggal dengan anak-anak selama bertahun-tahun,” kata Dr. Casebourne dari Early Intervention Foundation.
Statistik mengkhawatirkan: 1 dari 15 anak terpapar kekerasan pasangan intim setiap tahun, dan 90 persen dari anak-anak ini adalah saksi mata kekerasan tersebut. NSPCC memperkirakan bahwa 3,2 persen anak di bawah 11 tahun dan 2,5 persen anak berusia 11-17 tahun telah terpapar kekerasan domestik dalam setahun terakhir.
“Ini berarti bahwa, berpotensi, setidaknya 15.000 anak akan terpapar kekerasan domestik selama periode dua minggu Natal,” kata laporan NSPCC.
Di Indonesia, data spesifik tentang anak yang terpapar KDRT masih sangat terbatas. Namun, Unit PPA di berbagai daerah melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang sering terkait dengan lingkungan rumah tangga yang penuh kekerasan.
“Bayi dan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan sangat terpengaruh oleh peningkatan ketegangan dan konflik selama periode perayaan,” jelas Joy Walker-Jones. “1001 hari pertama, dari kehamilan hingga usia dua tahun, adalah periode krusial untuk perkembangan emosional dan fisik bayi. Stres di rumah tangga dapat memengaruhi tidur, makan, dan ikatan awal bayi.”
Anak-anak yang lebih tua mungkin merasa bertanggung jawab atas kekerasan, percaya mereka yang disalahkan karena “merusak perayaan tahun baru”. Rasa bersalah dan kecemasan yang salah tempat ini dapat meninggalkan luka yang bertahan lama.
Upaya yang Belum Cukup
Berbagai organisasi telah berupaya merespons krisis ini. Kemen PPPA meluncurkan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Beberapa daerah seperti Samarinda meluncurkan aplikasi SOPA (Sistem Online Pengaduan Perempuan dan Anak) untuk memudahkan pelaporan.
“Ada sisi positif dan negatif,” kata Ibnu Araby. “Positifnya, masyarakat semakin sadar dan berani melapor. Dengan adanya aplikasi SOPA, siapa pun dapat melaporkan kasus kekerasan, baik KDRT maupun kekerasan terhadap anak.”
Namun, peningkatan laporan tidak serta-merta berarti peningkatan perlindungan. “Kami masih kekurangan shelter, konselor terlatih, dan mekanisme perlindungan jangka panjang,” ungkap Desy Andriani. “Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat korban. Karenanya, mereka berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah.”
Selama periode liburan, tantangan menjadi lebih besar. “Penutupan sekolah untuk liburan juga berarti bahwa kesempatan bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan dan mengakses dukungan dibatasi,” kata laporan dari For Baby’s Sake Trust.
Banyak layanan dukungan seperti shelter dan hotline mungkin memiliki jam operasional yang dikurangi atau kekurangan staf, yang dapat membuat lebih menantang bagi korban untuk mencari bantuan atau melarikan diri dari situasi kekerasan.
Suara yang Dibungkam
Yang paling menyedihkan adalah banyak korban memilih diam. “Kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan domestik,” tegas Dian Ekawati. “Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihentikan.”
Namun, stigma sosial masih sangat kuat. “Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan, justru masih menjadi lokasi paling rentan bagi terjadinya kekerasan,” katanya.
Masyarakat sering menyalahkan korban atau menganggap KDRT sebagai “masalah internal keluarga” yang tidak perlu dibawa ke ranah publik. Korban yang melapor sering menghadapi pertanyaan seperti “Memangnya kamu buat salah apa sampai dipukul?” atau “Kenapa tidak sabar saja, namanya juga suami.”
“Korban KDRT memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan dari hukum,” tegaskan kajian yang dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Law and Justice Volume 3, Januari 2025. “Penting untuk diingat bahwa KDRT bukan salah korban.”
Kesimpulan
Ketika dunia merayakan pergantian tahun dengan penuh harapan, ribuan perempuan dan anak-anak Indonesia menghadapi realitas yang sangat berbeda. Bagi mereka, 1 Januari bukan menandai permulaan yang baru, melainkan kelanjutan dari siklus kekerasan yang sama.
Angka 1.010 kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang Januari-Oktober 2025 hanyalah puncak gunung es. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, kasus lainnya tidak pernah dilaporkan karena korban terjebak dalam siklus ketakutan, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial yang melanggengkan kekerasan.
Fenomena lonjakan KDRT pasca perayaan tahun baru adalah masalah kompleks yang melibatkan faktor psikologis, ekonomi, sosial, dan struktural. Tekanan finansial, konsumsi alkohol, ekspektasi sosial yang tidak realistis, kontak yang diperpanjang dengan pelaku, dan isolasi dari sistem dukungan menciptakan “badai sempurna” yang memicu kekerasan.
Namun, di balik kompleksitas ini, terdapat kegagalan sistemik yang lebih mendasar: budaya patriarki yang melanggengkan ketidaksetaraan gender, sistem hukum yang belum efektif melindungi korban, tidak adanya mekanisme restitusi yang memadai, dan minimnya layanan dukungan yang dapat diakses, terutama selama periode liburan ketika korban paling membutuhkannya.
Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa fenomena ini bukan baru di Indonesia. Malam Tahun Baru secara konsisten mencatat tingkat kekerasan pasangan tertinggi di berbagai negara: dari Amerika Serikat hingga Australia, dari Inggris hingga Indonesia. Ini adalah krisis global yang membutuhkan respons global.
Namun, pengetahuan tentang pola ini belum diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang efektif. “Penelitian ini signifikan karena akan membantu dalam mengalokasikan sumber daya layanan kesehatan dan strategi untuk pencegahan,” kata Dr. Khurana. Namun, alokasi sumber daya itu masih sangat kurang, terutama di Indonesia.
Yang dibutuhkan bukan sekadar kampanye kesadaran atau hotline tambahan selama periode liburan, meski itu penting. Yang dibutuhkan adalah transformasi sistemik: penguatan UU PKDRT dengan mekanisme restitusi yang efektif, pelatihan komprehensif untuk aparat penegak hukum, pembangunan shelter dan layanan dukungan yang memadai.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: