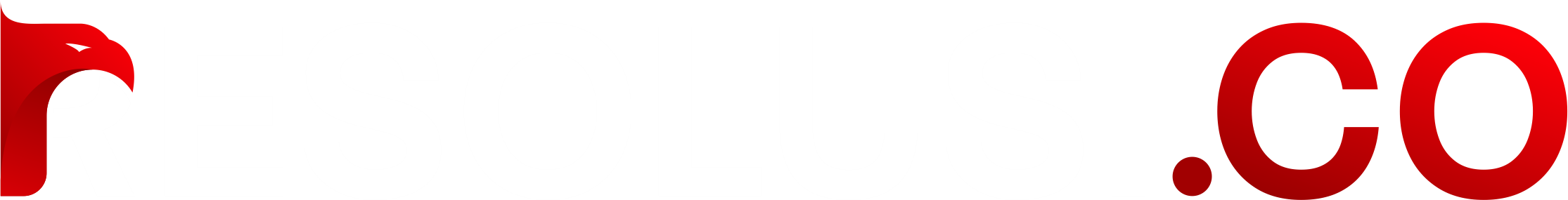Merdeka Tanpa Medali: Potret Hidup Lansia yang Tak Masuk Agenda Perayaan

- Kisah Samantra (110 tahun) dan Mbah Nuriyah (84 tahun) menggambarkan lansia desa yang terus bekerja demi bertahan hidup tanpa dukungan memadai, meski pernah melewati masa kolonial dan kesulitan panjang.
- Banyak lansia di Madura hidup dalam kerentanan: minim perlindungan sosial, tinggal sendirian, dan tidak terjangkau program bantuan meski angka kemiskinan wilayah ini tinggi.
- Bagi mereka, kemerdekaan bukan perayaan, melainkan kemampuan hidup layak hari demi hari—sebuah perjuangan senyap yang tidak tercatat negara.
 , Petang itu, beberapa menit sebelum pengeras suara di Langgar melantunkan adzan maghrib, Samantra duduk bersila di serambi rumah kayunya yang renta. Di tangannya, daun rokok kering dilinting pelan, tembakau tipis dari kebun sendiri diratakan dengan jari-jari tua yang bergetar pelan. Sekali dua kali batuk kecil menyela, tapi tak menghentikan rutinitas yang telah ia jalani sejak remaja.
, Petang itu, beberapa menit sebelum pengeras suara di Langgar melantunkan adzan maghrib, Samantra duduk bersila di serambi rumah kayunya yang renta. Di tangannya, daun rokok kering dilinting pelan, tembakau tipis dari kebun sendiri diratakan dengan jari-jari tua yang bergetar pelan. Sekali dua kali batuk kecil menyela, tapi tak menghentikan rutinitas yang telah ia jalani sejak remaja.
“Merokok itu teman tua,” gumamnya, sambil menyulut korek minyak. Asap tipis melayang ke udara, bersatu dengan kabut tipis yang menggantung di perbukitan Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
Samantra kini berusia 110 tahun. Ya, seratus sepuluh. Tak ada catatan akurat soal tanggal lahirnya, tapi ia masih ingat jelas suasana saat tentara Jepang datang ke desanya.
“Waktu itu saya sudah bisa bawa cangkul sendiri,” ujarnya. Ia tak pernah sekolah, tak bisa baca tulis latin, tapi ia fasih membaca Al-Qur’an dan beberapa kitab kuning. Santri otodidak, kata para tetangganya.
“Orang dulu kalau mau tahu apa-apa, ya ngaji. Bukan baca buku, tapi baca hidup,” ucapnya lirih.
Samantra tinggal sendiri. Istrinya wafat dua puluh tahun lalu, anak-anaknya merantau. Di usianya yang sangat senja, ia masih merawat sepetak kebun kecil—bukan untuk bisnis, hanya agar tetap bergerak. Ia tak pernah ikut upacara 17 Agustus, tak pernah diminta bicara di mimbar desa, tak masuk dalam daftar veteran.
“Saya bukan pejuang. Cuma petani. Tapi saya juga pernah lapar, pernah ngungsi karena takut diseret Jepang,” katanya.
Sementara itu, di sudut kecamatan lain, tepatnya di Longos, Gapura, Jawa Timur, ada Mbah Nuriyah, perempuan lansia 84 tahun, yang begitu bersemangat berkisah soal masa lampau tentang penjajah—yang tentu ia dengan dari almarhum bapaknya. Nuriyah adalah janda sejak muda.
Ia menghidupi dirinya dengan menjual sayur keliling desa. Sehari-hari, ia mendorong gerobak kecil berisi kangkung dan daun pisang, hasil panen dari halaman rumahnya yang sempit. “Kalau nggak kerja, siapa yang ngasih makan? Anak saya juga pas-pasan di kota,” katanya.
Mereka adalah wajah-wajah tua dari desa yang tidak masuk agenda perayaan. Mereka tak hadir dalam barisan upacara 17-an, tak terdata dalam penerima tunjangan lansia, tak dikenang sebagai veteran.
Tapi mereka juga pernah bertahan di bawah hegemoni dan kendali penjajahan, dalam paceklik panjang, dan dalam pembangunan yang tak pernah benar-benar mampir ke ladang mereka.
Tua di Tengah Kerentanan
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, lebih dari 12% penduduk lansia di kabupaten ini masih bekerja secara informal, sebagian besar di sektor pertanian dan perdagangan kecil.
Bagi pekerja informal, apalagi lansia, masa depan kerap diselimuti ketidakpastian. Tanpa jaminan kerja yang layak, mereka juga tak tersentuh perlindungan sosial—tak ada asuransi kesehatan, tak ada jaminan ketenagakerjaan, apalagi hari tua yang terjamin.
Mereka bekerja keras setiap hari, namun tetap berjalan di atas tali rapuh tanpa jaring pengaman. Meski begitu, hanya sebagian kecil dari mereka yang tercatat dalam program bantuan lansia dari pemerintah pusat atau daerah.
Secara nasional, jumlah lansia di Jawa Timur mencapai lebih dari 2 juta jiwa, dan lebih dari 20% di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023). Skema seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) memang ada, tapi pelaksanaannya sering tidak menjangkau desa-desa pinggiran seperti Payudan Dundang.
Program PKH Plus bagi lansia hanya mencakup sekitar 44.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 25 kabupaten, dengan distribusi yang belum merata.
Bahkan di Kabupaten Sumenep sendiri, dari total sekitar 13 ribu lansia yang terdata, hanya 170 orang saja yang menerima bantuan sosial khusus dari pemerintah daerah. Angka ini jelas memperlihatkan sebuah ketimpangan yang nyata antara kebutuhan dan perhatian yang diberikan.
Di satu sisi, keberadaan 13 ribu lansia ini mencerminkan betapa besar jumlah warga berumur yang seharusnya menjadi fokus utama dalam berbagai program sosial dan perlindungan.
Lansia adalah kelompok yang rentan, yang sering menghadapi tantangan kesehatan, keterbatasan mobilitas, dan keterbatasan ekonomi. Mereka seharusnya mendapatkan dukungan maksimal agar tetap dapat menjalani masa tua dengan sejahtera dan bermartabat.
Namun, di sisi lain, fakta bahwa hanya sebagian kecil dari mereka—kurang dari 2 persen— yang menerima bantuan sosial menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas kebijakan dan distribusi bantuan.
Apakah mekanisme pendataan sudah tepat? Apakah kriteria penerima bantuan sudah mencakup seluruh lansia yang benar-benar membutuhkan? Atau mungkin ada kendala lain, seperti kurangnya sumber daya, birokrasi yang rumit, atau bahkan kesenjangan informasi?
Narasi ini seolah mengajak kita untuk tidak hanya berhenti pada angka statistik, melainkan juga menggugah kesadaran kolektif bahwa lansia adalah bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan secara serius. Mereka bukan hanya angka dalam data, melainkan manusia dengan cerita, perjuangan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
Belum lagi, fenomena lansia ditinggal anak merantau juga menjadi realitas yang semakin umum. Bila ditelusuri lebih detial, tidak sedikit lansia pedesaan di Madura tinggal tanpa pendamping keluarga langsung. Sebagian hanya ditemani tetangga, sebagian lagi benar-benar hidup sendiri—seperti Samantra.
Menurut BPS, 9,38% lansia di Indonesia hidup sendirian, tanpa anggota keluarga lain (BPS, 2019). Angka ini bisa lebih tinggi di wilayah tertinggal seperti Madura, yang juga menghadapi tantangan geografis dan digital.
Madura, dengan bentangan ladangnya yang kering dan nama besar sebagai pulau garam, selama bertahun-tahun menyimpan ironi yang mencolok: kekayaan budaya dan kerja keras penduduknya berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraannya. Di tengah geliat pembangunan Jawa Timur, pulau ini masih menjadi salah satu wilayah dengan indeks kemiskinan tertinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Maret 2024, tingkat kemiskinan di empat kabupaten di Madura—Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—seluruhnya berada di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Sumenep, tempat Samantra dan Nuriyah tinggal, mencatat angka kemiskinan sebesar 17,78%, jauh di atas rata-rata Jawa Timur yang hanya 9,79%. Ini menjadikannya salah satu dari lima daerah termiskin di provinsi ini.
Kemiskinan di Madura bukan sekadar angka. Ia berwujud dalam jalan tanah yang rusak, sekolah dasar yang kekurangan guru, posyandu tanpa tenaga medis tetap, dan desa-desa yang masih memiliki akses jalan rusak Belum lagi, akses air bersih pun masih menjadi tantangan di sejumlah desa bagian selatan dan timur Madura.
Menurut laporan Bappeda Jatim, penyebab utama kemiskinan di Madura adalah rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya infrastruktur ekonomi dan digital. Hal-hal ini membuat penduduk seperti Samantra dan Nuriyah terjebak dalam siklus kerja keras dengan hasil yang tak sebanding.
Kemerdekaan Bukan Euforia
Pada titimangsa inilah, cerita tentang Samantra dan Nuriyah bukan sekadar kisah pribadi seorang lansia renta. Ia mewakili ribuan warga desa yang merasa berada di pinggiran Republik, yang setiap tahun melihat geliat kemerdekaan lewat televisi tetangga tapi tak pernah merasakan sentuhan konkret dari negara.
Kemerdekaan, bagi mereka, bukan sekadar simbol. Bukan bendera, bukan lagu kebangsaan, bukan barisan pramuka. Bukan euforia, bukan juga karnaval. Bagi Samantra dan Nuriyah, merdeka itu sederhana: bisa makan hari ini, bisa sehat sampai esok, bisa hidup tanpa menyusahkan anak cucu.
“Negara itu besar, tapi tak semua sudutnya disapu perhatian. Kami hidup di sudut yang dilupakan,” kata Samantra.
Setiap tahun, di bulan Agustus, desa-desa lain sibuk mengadakan lomba makan kerupuk dan tarik tambang. Di Payudan Dundang, tak ada panggung hias. Hanya daun tembakau yang menguning dan ladang jagung yang menanti hujan. Tak ada bendera besar yang dikibarkan.
Tapi di serambi rumah, Samantra masih menyalakan api tembakaunya—seperti menyala-nyalakan kenangan bahwa ia juga bagian dari Republik ini, meski tanpa medali.
Di Payudan Dundang, tak ada pahlawan yang disambut karpet merah. Tapi ada manusia-manusia biasa yang tetap hidup, tetap bekerja, tetap percaya, meski sejarah tak mencatat nama mereka. Mereka bukan veteran. Tapi mereka tahu rasa kalah, begitu paham rasa takut, dan hapal rasa lapar.
Di tengah upacara kenegaraan yang megah, ada jutaan orang tua seperti mereka yang tak pernah duduk di tribun kehormatan, tapi setiap hari berjuang dengan kesunyian dan kegetiran yang mendalam.
Lagipula, bukankah itu juga perjuangan?
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: