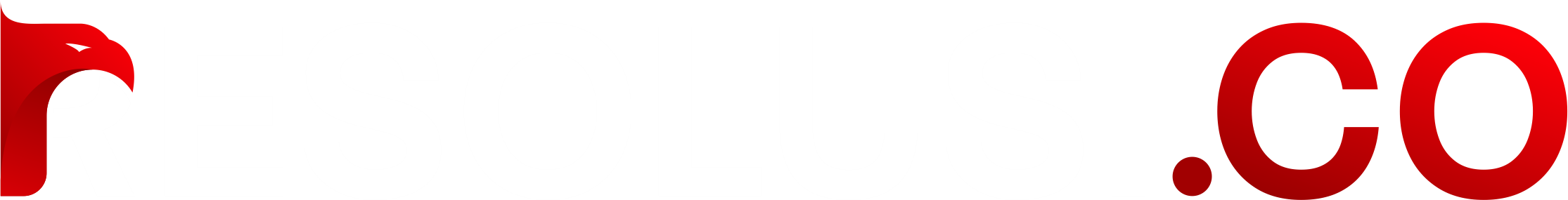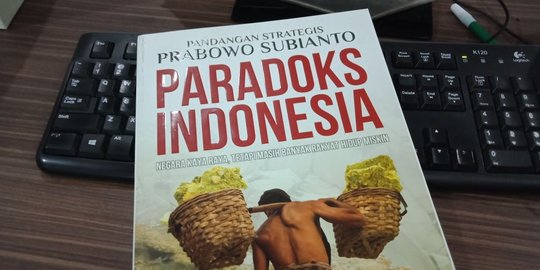Trauma-Informed Reporting: Melaporkan Trauma yang Tak Terlihat

- Bencana iklim di Indonesia bukan hanya menghancurkan infrastruktur dan menelan ribuan korban jiwa tetapi juga memicu depresi eco anxiety PTSD dan kehilangan identitas terutama pada kelompok rentan seperti warga pesisir remaja perempuan dan keluarga berpendapatan rendah
- Media masih bias pada dampak fisik dan ekonomi sementara dimensi kesehatan mental jarang diliput ditambah stigma serta rendahnya praktik peliputan sensitif trauma membuat penderitaan psikologis kian tak terlihat bahkan jurnalis pun rentan mengalami trauma dan moral injury
- Pers perlu bertransformasi melalui trauma informed reporting pencantuman layanan bantuan kesehatan mental serta pendekatan data dan solution journalism agar tidak sekadar menjadi saksi bencana tetapi menjadi penggerak perubahan yang memanusiakan korban krisis iklim
 , Beberapa waktu lalu, saat banjir bandang Aceh membunuh lebih 776 jiwa di penghujung 2025, kamera mengabadikan rumah runtuh, jalan terputus, dan arus deras. Di balik itu, ada kehancuran lain yang nyaris tak tertangkap lensa wartawan: seorang petani di Sumatra Barat yang tak bisa tidur sejak banjir dan lahar merenggut tetangganya setahun lalu; seorang nelayan di pesisir yang menangis diam-diam karena laut tempat ia mencari nafkah selama tiga dekade kini tampak menakutkan baginya; atau bahkan ribuan warga yang bertahan di pengungsian dengan tatapan kosong seolah alam telah merenggut masa depannya.
, Beberapa waktu lalu, saat banjir bandang Aceh membunuh lebih 776 jiwa di penghujung 2025, kamera mengabadikan rumah runtuh, jalan terputus, dan arus deras. Di balik itu, ada kehancuran lain yang nyaris tak tertangkap lensa wartawan: seorang petani di Sumatra Barat yang tak bisa tidur sejak banjir dan lahar merenggut tetangganya setahun lalu; seorang nelayan di pesisir yang menangis diam-diam karena laut tempat ia mencari nafkah selama tiga dekade kini tampak menakutkan baginya; atau bahkan ribuan warga yang bertahan di pengungsian dengan tatapan kosong seolah alam telah merenggut masa depannya.
Rentetan peristiwa itu, disadari atau tidak, Adalah wajah krisis yang wartawan liput, yaitu dampak kesehatan mental dari perubahan iklim. Riset terbaru Universitas Manchester dan Universitas Brawijaya Februari tahun lalu, menemukan fakta mengejutkan. Penduduk pesisir Indonesia yang tinggal di zona rawan bencana iklim memiliki risiko depresi 1,13 kali lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di luar zona tersebut.
Studi cross-sectional terhadap 642.419 orang dewasa Indonesia mengonfirmasi apa yang seharusnya sudah wartawan ketahui sejak awal: bencana iklim bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga kesehatan mental jutaan orang.
Data BNPB mencatat 2.998 bencana terjadi sepanjang 2025 hingga Desember, dengan 1.503 kasus banjir dan 218 tanah longsor. Angka resmi menyebutkan 1.269 orang meninggal, 575 hilang, dan hampir 10 juta mengungsi. Namun berapa yang mengalami eco-anxiety? Berapa yang menderita PTSD setelah menyaksikan rumah mereka tersapu banjir berkali-kali? Berapa warga Indonesia yang kehilangan identitas karena sawah mereka yang digarap tiga generasi kini tandus permanen? Tentu data ini tidak ada. Cerita ini pun tak pernah tertulis.
Universitas Indonesia 2024 lalu melakukan penelitian terhadap 1.108 remaja. Riset ini menemukan korelasi kuat antara eco-anxiety dan gangguan kecemasan umum. Perempuan, kelompok usia remaja, dan keluarga berpendapatan rendah, terhitung paling rentan. Dari kenyataan itu, berapa sih media yang secara konsisten meliput dimensi kesehatan mental dalam reportase bencana?
Problem mendasar kita adalah bias dalam definisi “dampak”. Ketika melaporkan banjir Aceh-Sumatera yang merenggut 1.157 jiwa pada akhir tahun kemarin, kita menghitung rumah rusak dan kerugian ekonomi. Kita mewawancarai kepala daerah dan ahli hidrologi. Tapi jarang sekali kita duduk dengan ibu rumah tangga yang sekarang panik setiap hujan deras, atau anak sekolah yang mimpi buruk tentang air. Kita mencatat korban tewas, tapi mengabaikan jutaan yang “mati” perlahan secara psikologis.
Jurnalis sendiri tidak kebal. Riset terhadap 1.000 jurnalis garda depan menunjukkan tingkat PTSD yang jauh lebih tinggi dibanding populasi umum. Meliput bencana berulang kali membawa beban moral tersendiri yang disebut “moral injury”, rasa sakit saat gagal melakukan sesuatu sesuai nilai moral kita. Seorang jurnalis iklim menonton kebijakan lingkungan dikebiri dari agenda politik sambil tahu persis konsekuensinya bagi masyarakat. Ini bukan sekedar frustrasi profesional, ini luka eksistensial.
Yang lebih memprihatinkan, stigma kesehatan mental di Indonesia membuat peliputan menjadi tabu ganda. Penelitian Dewan Pers 2024 menemukan 87% media online melanggar kode etik dalam penulisan isu sensitif seperti kekerasan seksual. Bayangkan, bagaimana mungkin media menangani isu kesehatan mental yang stigmanya lebih berat. Kita masih terjebak pada narasi “waras” versus “normal”, bukan spektrum kesehatan mental yang sebenarnya.
Perubahan iklim menciptakan kategori penderitaan psikologis baru. Solastalgia, istilah yang diciptakan filsuf Australia Glenn Albrecht, menggambarkan kesedihan mendalam akibat hilangnya identitas lingkungan. Bayangkan petani kopi Gayo yang menyaksikan tanaman warisan nenek moyangnya mati karena pola hujan berubah. Ini bukan sekadar kerugian ekonomi, ini kehilangan identitas, makna hidup, koneksi spiritual dengan tanah.
Pers punya peran krusial namun kita belum menjalankannya. Pertama, kita harus melatih jurnalis untuk trauma-informed reporting. Prinsip “do no harm” bukan hanya berlaku untuk identitas korban kekerasan seksual, tapi juga untuk mereka yang mengalami trauma iklim. Kedua, setiap artikel bencana harus mencantumkan informasi layanan kesehatan mental dan nomor krisis. Ketiga, kita perlu mengadopsi solution journalism yang tidak hanya melaporkan keputusasaan tapi juga resiliensi komunitas.
Data-driven journalism bisa menjadi senjata seorang wartawan. Visualisasi korelasi antara frekuensi bencana dan peningkatan kasus gangguan mental di daerah tertentu bisa memaksa pembuat kebijakan bertindak. Investigasi tentang ketiadaan layanan kesehatan mental di kabupaten rawan bencana adalah bentuk advokasi yang sah. Profil tenaga kesehatan mental yang bekerja dengan korban bencana adalah inspirasi yang kita butuhkan.
Bagiamanapun, setiap bencana meninggalkan jejak psikologis yang akan bertahan jauh lebih lama dari puing-puing yang kita foto. Momentum Hari Pers Nasional mestinya juga menjadi agenda untuk pertanyaan bukan lagi pada soal “seberapa bebas pers kita?”, tapi “seberapa bertanggung jawab kita meliput krisis yang menentukan masa depan bangsa ini?”
Tugas wartawan memang bukan lagi sekadar melaporkan apa yang terlihat, tapi mengungkap apa yang tersembunyi. Trauma iklim adalah epidemi diam-diam yang menggerus kesehatan mental jutaan orang. Di tengah kompetisi clickbait dan deadline yang mematikan, kita lupa bahwa jurnalisme terbaik adalah yang memanusiakan mereka yang terpinggirkan, termasuk mereka yang menderita diam-diam akibat alam.
Saat bencana hidrometeorologi meningkat drastis setiap tahun, pilihan kita sebagai jurnalis menjadi jelas. Kita bisa terus menulis laporan permukaan tentang jumlah korban dan kerusakan fisik, atau kita bisa menyelami lebih dalam dan menceritakan kisah-kisah yang benar-benar penting, kisah tentang ketahanan dan kerentanan manusia menghadapi perubahan yang tak terelakkan.
Karena itu, bagi Saya, pers Indonesia hari ini punya dua pilihan: sekadar menjadi saksi atau justru menjadi sinyal perubahan yang memberi suara pada penderitaan yang kadang tak terlihat ini.