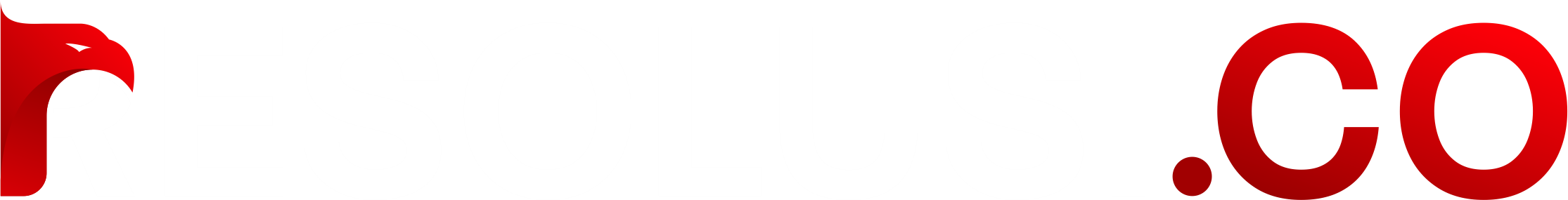Denny JA: NU Punya Dua Nakhoda, Umat Bingung Ikut Siapa?

Ringkasan Penting
- NU mengalami krisis kepemimpinan dengan dua legitimasi berbeda: Gus Yahya menilai pencopotannya cacat prosedur, Zulfa Mustofa ditetapkan sah oleh pleno Syuriyah
- Konflik diperparah isu konsesi tambang yang muncul pertama kali dalam sejarah modern NU, mengubah sifat konflik dari struktural menjadi perebutan sumber daya alam
- Pelajaran 1984: NU pernah selamat dari krisis lewat kearifan kiai sepuh seperti KH Ahmad Siddiq yang mengutamakan persatuan di atas ego
 , JAKARTA – Nahdlatul Ulama tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang belum pernah terjadi dalam sejarah panjang organisasi Islam terbesar di Indonesia. KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU cacat prosedur, sementara KH Zulfa Mustofa yang baru ditetapkan sebagai Penjabat Ketua Umum meyakini pengangkatannya sah menurut rapat pleno Syuriyah.
, JAKARTA – Nahdlatul Ulama tengah menghadapi krisis kepemimpinan yang belum pernah terjadi dalam sejarah panjang organisasi Islam terbesar di Indonesia. KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU cacat prosedur, sementara KH Zulfa Mustofa yang baru ditetapkan sebagai Penjabat Ketua Umum meyakini pengangkatannya sah menurut rapat pleno Syuriyah.
Dualisme kepemimpinan ini menciptakan kebingungan masif di tengah umat. Dari desa hingga kota, dari grup WhatsApp jamaah hingga pesantren, satu pertanyaan menggantung: siapa sesungguhnya yang memimpin PBNU hari ini?
Analis politik Denny JA dalam opininya yang diterbitkan 11 Desember 2025 menilai krisis ini bukan sekadar masalah administratif.
“Ini adalah kegelisahan moral, karena NU bukan organisasi biasa. Ia adalah urat nadi spiritual bangsa tempat puluhan juta jiwa menambatkan keyakinan, tradisi, dan harapan,” tulis Denny JA.
Ketika rumah besar ini bergetar, dampaknya merembet ke seluruh lapisan umat. Di desa, jamaah bertanya harus mengikuti siapa. Di pesantren, santri ragu nama ketua umum mana yang harus disebut dalam ceramah. Di kota, pengurus cabang menunggu kepastian yang tak kunjung datang.
Organisasi yang didirikan 1926 ini memiliki otoritas simbolik yang kuat bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan para ulama yang memimpinnya. Ketika otoritas itu goyah, yang terancam bukan hanya struktur organisasi, tetapi ruh jam’iyah itu sendiri.
Pelajaran dari Krisis 1984
Konflik kepemimpinan sejatinya bukan hal baru bagi NU. Tahun 1984, organisasi ini dihadapkan pada ketegangan besar ketika Gus Dur membawa NU kembali ke Khittah 1926. Sebagian elite ingin NU tetap menjadi kekuatan politik, sebagian lain menghendaki kembali pada ruh moral dan sosial.
Suasana memanas di Muktamar Situbondo, aspirasi bersilang tajam. Namun yang menyelamatkan NU bukan hitungan suara atau strategi politik, melainkan kearifan kiai-kiai sepuh. KH Ahmad Siddiq, KH Ali Maksum, dan KH As’ad Syamsul Arifin menjadi jangkar etika ketika ombak politik datang terlalu tinggi.
Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam bukunya “Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967”, setiap pergolakan besar di tubuh NU selalu memuat dua lapis drama: perebutan posisi di permukaan, dan pencarian kompas moral di kedalaman.
“Dari situlah NU belajar bahwa konflik bukan kutukan. Ia dapat menjadi pintu pembaruan, asal dibuka dengan keteduhan jiwa,” tulis Denny JA mengutip pelajaran sejarah tersebut.
Yang membuat krisis kali ini berbeda adalah munculnya isu konsesi tambang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern NU, publik mendengar desas-desus tentang kepentingan ekonomi yang dikaitkan dengan konflik kepemimpinan. Meski banyak tokoh menolak tegas dan isu belum terverifikasi sepenuhnya, ia tetap menyebar di ruang publik.
“Isu ini mengguncang karena menyentuh akses kekayaan alam, sesuatu yang jauh lebih eksplosif dari sekadar perebutan posisi struktural,” ungkap Denny JA.
Jika NU terseret dalam pusaran tambang, kepercayaan moral umat ikut dipertaruhkan. Konflik bukan lagi soal siapa ketua umum yang sah, tetapi apa yang sesungguhnya diperebutkan di balik layar.
Kekuatan terbesar NU justru lahir ketika organisasi ini melepaskan diri dari cengkeraman politik praktis dan kepentingan material sempit. Ketika berdiri di atas Khittah, NU memegang otoritas simbolik yang membuatnya didengar bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan.
“Ketika otoritas itu terkikis oleh tarik-menarik sumber daya alam, yang terancam bukan hanya struktur, tetapi ruh jam’iyah,” tegas Denny JA.
Krisis kepemimpinan PBNU hari ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi ketua umum. Ia tentang wajah Islam Nusantara di mata umat dan bangsa, tentang keutuhan tradisi, tentang Khittah yang dulu diperjuangkan dengan air mata dan ijtihad.
Sejarah mencatat berkali-kali NU selalu mampu menemukan cahayanya kembali, bahkan di tengah kegelapan.
“Tetapi itu hanya terjadi ketika para pemimpinnya memilih persatuan di atas ego, kedewasaan di atas ambisi, dan Khittah di atas manuver sesaat,” tulis Denny JA menutup analisisnya.
Publik menunggu, bangsa menunggu, jutaan santri menunggu. Mereka menunggu NU yang satu, bukan dua. NU yang bulat, bukan terbelah. NU yang kembali menjadi pelita moral bangsa, bukan sekadar pemain di gelanggang kekuasaan. Persatuan NU bukan hanya kebutuhan organisasi, ia adalah kebutuhan Indonesia.
Jangan Lewatkan Update Terbaru!
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News dan WhatsApp Channel