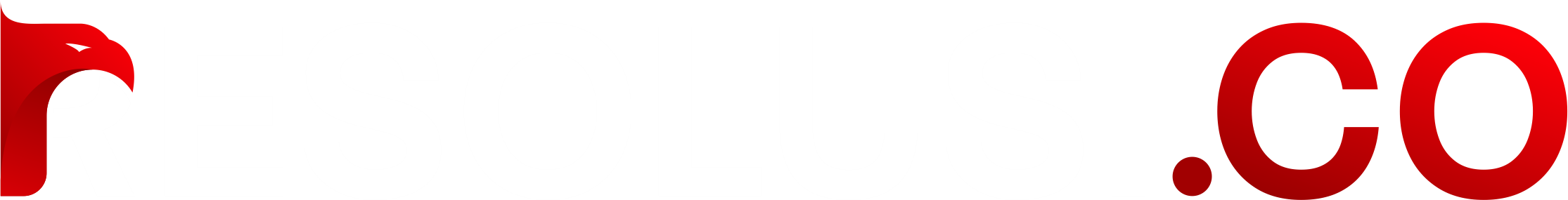Ketika Alam Menagih Hutang Manusia: Refleksi Atas Bencana Alam yang Tragis di Sumatera

 , Pada akhir November 2025, ketika air banjir membawa kayu-kayu gelondongan mengalir melewati kampung-kampung di Sumatera, sesuatu yang “tragis” telah terjadi. Bukan sekadar bencana material, bukan hanya angka-angka korban yang terus bertambah, tetapi sebuah pertanyaan fundamental tentang siapa sesungguhnya yang bersalah ketika langit menangis menghancurkan rumah. Kayu-kayu itu—pohon-pohon yang dulu berdiri tegak mempertahankan tanah, menjaga air, menjaga napas bumi—kini terbawa arus sebagai saksi bisu dari sebuah kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
, Pada akhir November 2025, ketika air banjir membawa kayu-kayu gelondongan mengalir melewati kampung-kampung di Sumatera, sesuatu yang “tragis” telah terjadi. Bukan sekadar bencana material, bukan hanya angka-angka korban yang terus bertambah, tetapi sebuah pertanyaan fundamental tentang siapa sesungguhnya yang bersalah ketika langit menangis menghancurkan rumah. Kayu-kayu itu—pohon-pohon yang dulu berdiri tegak mempertahankan tanah, menjaga air, menjaga napas bumi—kini terbawa arus sebagai saksi bisu dari sebuah kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana selama empat belas hari, mulai 27 November hingga 10 Desember 2025. Keputusan ini adalah pengakuan administratif atas kecatatan sebuah wilayah. Tetapi dalam keputusan itu, tersembunyi pertanyaan yang jauh lebih pelik: apakah empat belas hari cukup untuk memahami mengapa bencana datang? Apakah penandatanganan surat keputusan mampu mengubah struktur kesalahan yang telah mengakar dalam logika ekonomi dan pembangunan yang salah arah?
Ketika Cuaca Menjadi Alibi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengatakan bahwa banjir di Sumatera disebabkan oleh hujan ekstrem akibat fenomena siklon tropis. Ini benar, tentu saja. Cuaca ekstrem adalah realitas iklim yang tidak bisa disangkal. Tetapi ketika kita mengatakan itu adalah penyebab utama, kita melakukan sesuatu yang cukup berbahaya, kita mengabsurdkan tanggung jawab manusia di balik layar. Kita menciptakan narasi yang nyaman bahwa ini adalah bencana alam murni, sesuatu yang di luar kontrol, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.
Inilah liciknya bahasa politisi itu. Dia mengambil kejadian kompleks, yang melibatkan keputusan manusia, kebijakan, dan pilihan ekonomi, lalu menyatakannya sebagai fenomena meteorologi yang netral. Seolah-olah langit yang menurunkan air adalah pelaku tunggal, sementara manusia hanya korban pasif dari nasib yang buruk.
Tetapi Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (WALHI Sumut) berbicara dengan cara yang berbeda. Mereka menunjukkan citra satelit hutan yang gundul. Mereka menunjukkan kayu gelondongan yang terbawa arus—kayu yang sebelumnya ditebang oleh tangan manusia. Dan mereka berkata, ini bukan hanya cuaca ekstrem. Ini adalah kesinambungan dari keputusan-keputusan politik dan ekonomi yang telah mengubah lanskap, menguras kapasitas tanah untuk menyerap air, menghilangkan akar-akar yang dulu menahan longsor.
Inilah perbedaan antara menjelaskan sesuatu dan memahami sesuatu. Penjelasan adalah penyederhanaan yang menghibur. Pemahaman adalah penghargaan atas kompleksitas yang menyakitkan.
Ekosistem Batang Toru dan Apa yang Telah Kita Korbankan
Manajer Advokasi WALHI Sumatera Utara berbicara tentang ekosistem Batang Toru, satu dari beberapa sisa hutan tropis asli di kawasan itu. Ekosistem ini kaya dengan flora dan fauna langka, keanekaragaman yang telah disimpan selama ribuan tahun. Tetapi dalam hitungan dekade, melalui keputusan-keputusan administratif yang dituangkan dalam bentuk izin-izin dan alokasi lahan, banyak bagian dari kekayaan ini telah dialihfungsikan.
Alih fungsi lahan, sebuah frasa netral yang dengan mudah kita gunakan dalam laporan pemerintah, yang adalah eufemisme untuk penghancuran. Ketika hutan dijadikan perkebunan, ketika pohon dipotong untuk keuntungan jangka pendek, ketika resapan air digantikan dengan tanah yang keras dan tandus, kita tidak sekadar mengubah penggunaan lahan. Kita menghancurkan suatu sistem yang telah bekerja selama jutaan tahun.
Dan kemudian, ketika itu terjadi, ketika hujan datang dan tanah tidak bisa lagi menyerap air, ketika longsor terjadi karena tidak ada akar yang menahan, ketika kayu gelondongan terbawa arus membawa abu-abu kerusakan lalu kita terkejut. Kita menyebut ini bencana alam yang tak terduga. Padahal, itu adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari keputusan-keputusan yang telah kita buat.
Jaka Kelana dari WALHI mengatakan bahwa bencana yang mengetikan ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan bencana ekologis. Ini adalah pernyataan penting. Karena ketika sesuatu adalah bencana ekologis, itu berarti ada pihak yang bertanggung jawab. Itu berarti ada sistem yang telah gagal. Itu berarti ada keputusan-keputusan yang harus dipertanyakan.
Angka-Angka dan Apa yang Tersembunyi di Dalamnya
Hingga 27 November 2025, bencana ini telah menewaskan empat puluh delapan jiwa di Sumatera Utara, dengan delapan puluh delapan orang hilang. Jumlah ini akan terus bertambah karena pencarian masih berlangsung. Ada seribu seratus enam puluh delapan orang yang harus meninggalkan rumah mereka, mencari keselamatan di tempat lain, membawa dengan mereka kenangan tentang hidup yang kemarin masih normal.
Angka-angka ini adalah abstraksi dari penderitaan konkret. Di balik setiap angka adalah seorang ibu yang kehilangan anak, seorang anak yang mencari ayah di antara batu dan lumpur. Tetapi dalam perjalanan angka-angka ini melalui laporan resmi, melalui siaran pers, dan melalui berita yang dimakan media, mereka menjadi data statistik. Mereka menjadi “korban bencana” bukan “manusia yang kehilangan segalanya.”
Ini adalah bagian lain dari realitas modern, yakni kita mengubah kebencian manusia menjadi angka yang dapat ditangani, yang dapat diatur dalam kolom-kolom spreadsheet, yang dapat dilupakan setelah berita bergeser ke kejadian berikutnya.
Tetapi ada sesuatu yang penting dalam angka-angka. Ada pola. Korban terbanyak di Tapanuli Selatan—tujuh belas orang. Kemudian Tapanuli Utara dengan sembilan orang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah wilayah yang telah mengalami eksploitasi hutan paling intensif, wilayah di mana ekosistem Batang Toru tersebar. Kayu gelondongan yang mengalir membawa jejak dari manusia-manusia yang telah menebang pohon, dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan di kantor-kantor kabupaten dan provinsi, dari kebijakan yang mengutamakan ekonomi pendek atas ekologi jangka panjang.
Status Tanggap Darurat dan Apa yang Hilang
Ketika gubernur menetapkan status tanggap darurat, dia mengaktifkan mekanisme birokrasi yang dirancang untuk merespons keadaan darurat. Dana dilepas. Koordinasi diintensifkan. Instansi-instansi dimobilisasi untuk pencarian dan penyelamatan.
Ini adalah hal yang baik. Tentu saja, penyelamatan nyawa adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Tetapi ada yang hilang dalam sistem respons darurat ini—ada yang tertinggal dalam logika “tanggap darurat” yang berlaku selama empat belas hari. Penyelamatan adalah tindakan jangka pendek. Tetapi masalah ekologi yang berupa eksploitasi alam itu sendiri adalah masalah jangka panjang.
Ketika empat belas hari berlalu, status darurat akan dicabut. Kembali ke kehidupan normal. Tapi apa yang normal? Adalah normal bahwa hutan masih gundul. Adalah normal bahwa ekosistem Batang Toru masih terancam. Adalah normal bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengabaikan ekologi masih terus berjalan. Adalah normal bahwa tahun depan, ketika musim hujan tiba lagi, banjir akan datang lagi.
WALHI mengingatkan bahwa bencana serupa muncul setiap tahun, terutama ketika memasuki musim hujan. Ini adalah pengakuan yang sangat penting. Ini berarti bahwa yang kita panggil “bencana” adalah sebenarnya pola. Ini bukan pengecualian. Ini adalah norma yang telah kita ciptakan melalui pilihan-pilihan yang kita buat tentang bagaimana kita ingin hidup dengan alam.
Pertanyaan yang Harus Ditanyakan
Di sini, di antara kayu gelondongan yang mengalir dan rumah-rumah yang tertimbun lumpur, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Siapa yang membuat keputusan untuk menebang pohon? Siapa yang memberikan izin? Siapa yang menerima keuntungan? Dan yang paling penting, mengapa logika ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek masih lebih kuat daripada logika ekologi yang mengingatkan kita tentang tanggung jawab jangka panjang terhadap bumi?
Pemerintah mengatakan akan menolong. Tetapi menolong saat ini bukan apa yang diperlukan sama sekali. Yang diperlukan adalah transformasi struktur. Yang diperlukan adalah keputusan untuk tidak lagi mengorbankan hutan demi keuntungan. Yang diperlukan adalah keberanian untuk mengatakan tidak kepada alih fungsi lahan, untuk melindungi ekosistem Batang Toru, untuk memilih jalan pembangunan yang tidak didasarkan pada penghancuran.
Kayu gelondongan yang mengalir di air banjir adalah simbol. Simbol dari pohon yang dulu hidup, dari ekosistem yang dulu utuh, dari masa depan yang telah kita potong sebelum dia sempat tumbuh. Mereka adalah saksi dari kelalaian kita, dari cara kita telah hidup seolah-olah hutang ekologis tidak perlu dibayar.
Tetapi hutang selalu membayar sendiri. Dan saat membayar, dia datang dengan cara yang paling brutal: melalui kehilangan jiwa, melalui kehancuran rumah, melalui penderitaan manusia yang tidak bersalah.
Empat belas hari adalah waktu yang terlalu singkat untuk memahami ini. Tetapi mungkin, dalam keheningan di antara puing-puing, dalam menunggu kabar dari mereka yang hilang, dalam membangun kembali rumah di tanah yang telah berkhianat, ada kesempatan untuk berpikir kembali tentang siapa kita, tentang bagaimana kita ingin hidup, dan tentang apakah kita benar-benar siap untuk membayar hutang alam yang telah kita perbuat.
Jangan Lewatkan Update Terbaru!
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News dan WhatsApp Channel