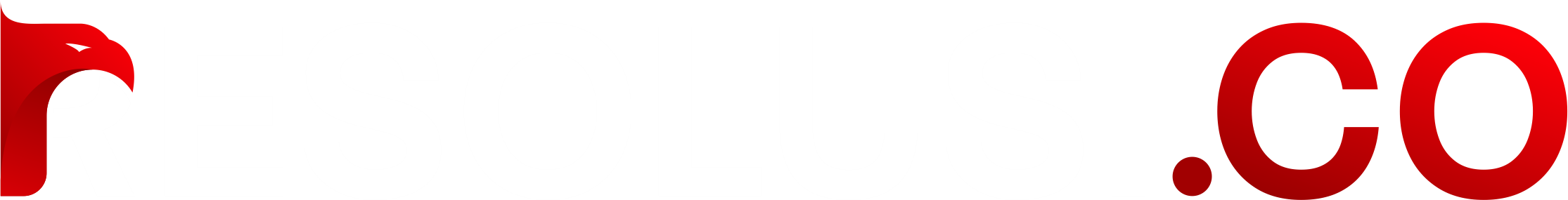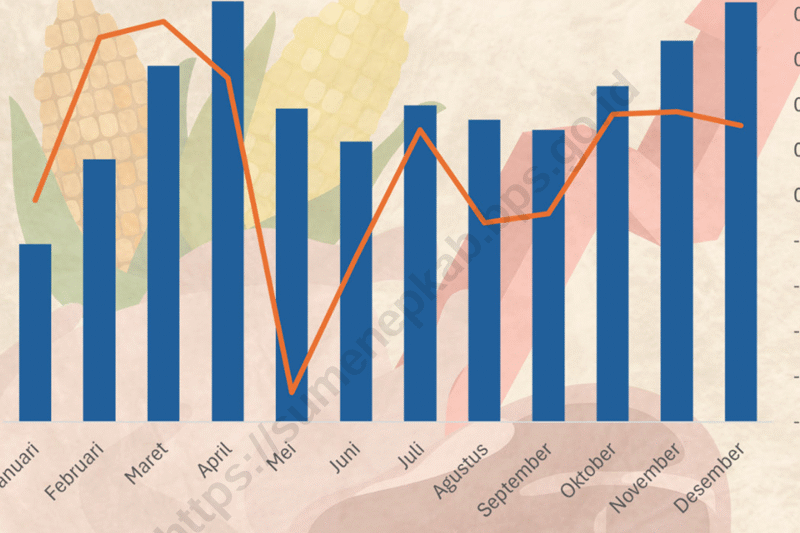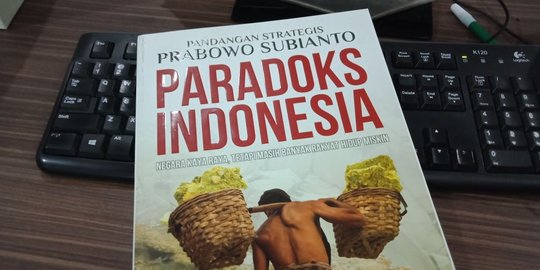Belajar Kembali dari Pinggiran: Sebuah Refleksi Satu Tahun Sekolah Hompimpa

- Di wilayah seperti Gili Iyang, keterbatasan fasilitas menunjukkan bahwa yang paling penting adalah ekosistem belajar. Hompimpa menghadirkan ruang di mana keluarga, relawan, dan anak-anak terlibat dalam proses pendidikan sebagai kerja sosial
- Semangat ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire: anak adalah subjek belajar. Di Hompimpa, membaca menjadi pengalaman menyenangkan, bukan tekanan akademik
- Hompimpa membuktikan bahwa pendidikan yang memerdekakan tidak harus besar dan mewah. Ia tumbuh dari kepedulian, konsistensi, dan keberanian percaya pada anak-anak
 , Kegelisahan sering kali menjadi titik mula perubahan. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sekolah Hompimpa lahir dari kegelisahan yang sederhana sekaligus getir: rendahnya kepedulian terhadap pendidikan di tingkat paling dasar. Di desa-desa, terutama di wilayah kepulauan seperti Gili Iyang, buku bacaan anak hampir tak pernah menjadi prioritas. Beberapa sekolah bahkan nyaris tak memiliki perpustakaan yang layak. Ironis, ketika pendidikan terus digembar-gemborkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
, Kegelisahan sering kali menjadi titik mula perubahan. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sekolah Hompimpa lahir dari kegelisahan yang sederhana sekaligus getir: rendahnya kepedulian terhadap pendidikan di tingkat paling dasar. Di desa-desa, terutama di wilayah kepulauan seperti Gili Iyang, buku bacaan anak hampir tak pernah menjadi prioritas. Beberapa sekolah bahkan nyaris tak memiliki perpustakaan yang layak. Ironis, ketika pendidikan terus digembar-gemborkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
Hompimpa tidak hadir sebagai sekolah dalam pengertian formal. Ia tumbuh sebagai ruang belajar komunitas yang lebih santai, lebih inklusif, dan lebih ramah anak. Lebih tepatnya, Hompimpa adalah taman bacaan masyarakat. Anak-anak datang tanpa seragam, tanpa tekanan nilai, tanpa rasa takut pada kata “salah”. Mereka membaca, bermain, mendengarkan cerita, dan belajar bersama. Sampai hari ini, ada sekitar 500 buku anak bermutu serta ratusan buku bacaan fiksi, ilmiah, dan populer menjadi pintu masuk menumbuhkan minat baca anak-anak.
Pengalaman ini mengingatkan kita pada gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak”. Pendidikan, bagi Ki Hajar, bukan proses memaksa, apalagi menekan, melainkan menuntun, memberi arah tanpa mencabut sekecil apapun yang namanya kebebasan. Prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani terasa hidup di Hompimpa. Anak-anak tidak digurui, tetapi didampingi; tidak dihakimi, tetapi dipercaya. Mereka adalah subjek yang mencari keinginannya sendiri.
Hompimpa sekaligus mengajak kita meninjau ulang cara kita memaknai pendidikan. Pendidikan tidak pernah semata urusan sekolah. Pendidikan adalah kerja-kerja sosial. Ketika pendidikan gagal menjangkau anak-anak di desa dan kepulauan, persoalannya bukan hanya kurikulum atau kualitas guru, melainkan rapuhnya ekosistem belajar. Sekolah kerap bekerja sendirian, sementara rumah dan lingkungan kehilangan peran sebagai ruang pendidikan.
Dalam banyak keluarga, rumah belum sepenuhnya menjadi ruang belajar yang aman dan menyenangkan. Buku jarang tersedia, orang tua sibuk dengan persoalan ekonomi, dan belajar sering dipahami sebatas pekerjaan rumah yang diberikan guru pada siswa. Padahal, keluarga adalah sekolah pertama. Di sanalah anak belajar rasa aman, percaya diri, dan kegembiraan dalam mengenal dunia. Hompimpa mencoba mengisi celah ini dengan melibatkan orang tua dan lingkungan sebagai bagian dari proses belajar.
Membaca, dalam konteks ini, perlu dipahami sebagai praktik budaya, bukan sekadar keterampilan teknis. Rendahnya minat baca kerap disalahkan pada anak, seolah mereka malas atau tidak tertarik. Padahal, seperti diingatkan banyak kajian pendidikan kritis, minat tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari kebiasaan, akses, dan relasi. Anak-anak mencintai buku karena buku hadir dalam hidup mereka, bukan karena diwajibkan.
Ini mungkin terlalu terburu-buru, bila dikatakan pendekatan Hompimpa sejalan dengan gagasan Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan. Sebagaimana Freire mengkritik pendidikan yang hanya menabungkan pengetahuan ke kepala murid, tanpa dialog dan pengalaman. Pendidikan, bagi Freire, seharusnya memanusiakan—membuka kesadaran, bukan menundukkan. Sejauh ini, di Hompimpa, anak-anak tidak diperlakukan sebagai wadah kosong, tetapi sebagai subjek belajar yang aktif, dengan pengalaman dan imajinasi mereka sendiri.
Konteks kepulauan seperti Gili Iyang memperlihatkan dengan jelas ketimpangan pendidikan. Jarak geografis dari pusat kebijakan membuat banyak program terasa jauh dari realitas lokal. Fasilitas terbatas, distribusi buku tidak merata, dan dukungan literasi sering kali bersifat seremonial. Namun, justru di ruang-ruang pinggiran inilah pendidikan berbasis komunitas menemukan relevansinya.
Hompimpa membuktikan bahwa pendidikan alternatif tidak selalu harus menunggu negara hadir secara sempurna. Hal itu bisa tumbuh dari inisiatif warga, dari kegelisahan sosial, dan dari kesadaran kolektif akan pentingnya masa depan anak-anak. Dalam skala kecil, Hompimpa sedang melakukan kerja kebudayaan: melawan normalisasi kemiskinan literasi dan menantang anggapan bahwa anak desa cukup belajar dari buku paket semata.
Pada akhirnya, pendidikan selalu berkaitan dengan harapan. Ki Hajar Dewantara pernah menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia lahir dan batin. Hompimpa, dengan segala keterbatasannya, sedang merawat semangat itu. Pengalaman selama bergiat di Hompimpa menemukan ruang-ruang lain, bahwa pendidikan yang memerdekakan tidak harus mewah, tetapi harus manusiawi. Di sanalah pendidikan kembali pada hakikatnya: menemani manusia bertumbuh dengan martabat dan empati.
Hompimpa memang bukan solusi tunggal bagi persoalan pendidikan di desa dan kepulauan. Namun, kehadirannya memberi pelajaran penting, bahwa pendidikan yang baik lahir dari kepedulian, dialog, dan keberanian untuk percaya pada anak-anak. Dari ruang kecil seperti taman baca, kita justru diperlihatkan bagaimana perubahan kerap dirintis dari pinggiran: melalui anak-anak yang belajar tanpa tekanan dan rasa takut, orang tua yang perlahan hadir dalam proses tumbuh kembang pengetahuan, serta komunitas yang mulai menyadari bahwa belajar bukan sekadar kewajiban, melainkan pengalaman sosial yang membahagiakan dan memulihkan harapan.
Di tengah segala keterbatasan, Hompimpa mengingatkan kita pada satu hal mendasar: pendidikan yang membebaskan berakar pada kemanusiaan. Tumbuh dari relasi yang setara, dari kepercayaan pada daya hidup anak, dan dari kesediaan komunitas untuk hadir serta mendampingi. Dari ruang sederhana itu, lahir keberanian untuk membayangkan masa depan yang lebih adil, di mana belajar menjadi pengalaman yang bermakna, bermartabat, dan membuka kemungkinan baru bagi setiap anak.