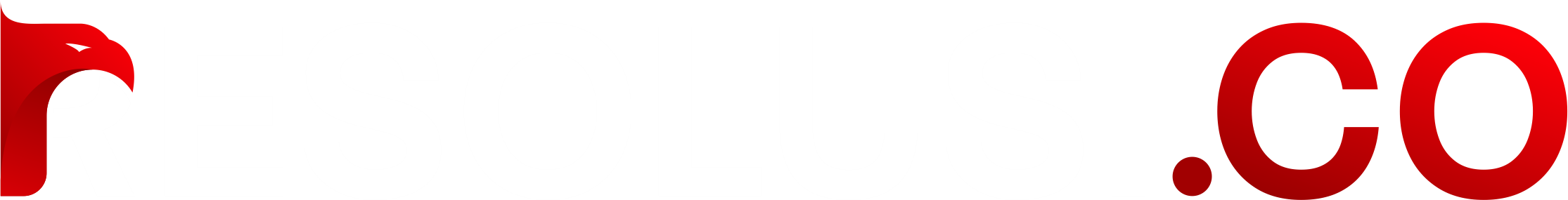Catatan tentang Dito, Ridwan Kamil, Nasib dan Pertemanan

 , Ada masa ketika seseorang mudah disukai.
, Ada masa ketika seseorang mudah disukai.
Namanya sering muncul. Dipuji. Diharapkan. Banyak orang ingin berada di sekitarnya.
Dito Ariotedjo dan Ridwan Kamil pernah berada di masa itu. Dengan latar yang berbeda, keduanya sama-sama pernah dianggap jawaban. Yang satu dipandang sebagai wajah muda di pemerintahan. Yang lain dilihat sebagai pemimpin yang terasa dekat dan mudah dipahami.
Lalu waktu berjalan.
Dan tidak selalu membawa kabar baik.
Belakangan ini, nama mereka kembali dibicarakan. Bukan karena kebijakan atau kerja yang bisa dihitung. Melainkan urusan pribadi. Rumah tangga. Isu yang berkembang ke mana-mana dan sering kali dibicarakan tanpa batas.
Saya tidak tertarik menentukan siapa benar dan siapa salah. Itu urusan yang cepat melelahkan. Yang lebih menarik justru sikap kita sebagai penonton. Betapa mudah kita mengubah cara memandang seseorang ketika hidupnya tidak lagi terlihat baik-baik saja.
Dulu dipuja.
Sekarang diperiksa dari segala sisi.
Di titik seperti ini, nasib terasa bekerja tanpa peringatan. Ia bisa mengangkat seseorang, lalu menurunkannya begitu saja. Ketika posisi bergeser, orang-orang yang dulu datang membawa pujian perlahan menghilang. Tidak selalu karena jahat, sering kali karena tidak tahu harus bersikap bagaimana.
Barangkali di situlah arti berbuat baik yang sebenarnya. Bukan supaya dikenal, tapi supaya tidak sendirian ketika keadaan tidak lagi memihak. Kita tidak pernah tahu kapan hidup berubah arah. Yang bisa kita siapkan hanyalah cara kita memperlakukan orang lain.
Tulisan ini bukan pembelaan. Juga bukan penilaian. Ini sekadar pengingat kecil bahwa tidak ada posisi yang benar-benar aman. Hari ini kita menonton hidup orang lain, besok bisa jadi giliran kita yang diperbincangkan.
Ada hal lain yang sering luput kita sadari. Ketika seseorang berada di atas, kesalahannya sering diberi alasan. Kita menyebutnya manusiawi, wajar, atau sekadar kekhilafan. Tetapi ketika posisinya bergeser, kesalahan yang sama berubah menjadi cacat. Ukurannya tidak lagi sama. Kita menilai dengan jarak yang lebih dekat, bahkan terlalu dekat.
Mungkin karena itu kekuasaan, jabatan, dan popularitas bukan sekadar soal posisi, tapi juga pelindung. Ia memberi lapisan yang membuat seseorang tampak lebih hangat dari luar. Ketika lapisan itu hilang, barulah dingin terasa. Dan tidak semua orang siap menghadapi perubahan itu.
Di sini, empati seharusnya bekerja. Bukan untuk membenarkan semua hal, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap orang membawa bebannya sendiri. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Kita hanya melihat potongan kecil, lalu merasa cukup untuk menilai keseluruhan hidup seseorang.
Maka barangkali yang paling masuk akal adalah menahan diri. Tidak ikut menambah suara ketika keadaan sudah penuh oleh omongan. Tidak ikut menunjuk ketika seseorang sedang jatuh. Sebab hidup ini aneh. Hari ini kita berdiri sebagai penonton, besok bisa saja kita yang berada di tengah lapangan, dinilai oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar mengenal kita.
Dan pada saat itu, kita akan tahu siapa yang datang karena jabatan, dan siapa yang bertahan karena hubungan.
Seluruh isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi hanya bertindak sebagai fasilitator publikasi dan tidak bertanggung jawab atas opini, data, atau klaim yang disampaikan.
✍ Kirim Tulisan