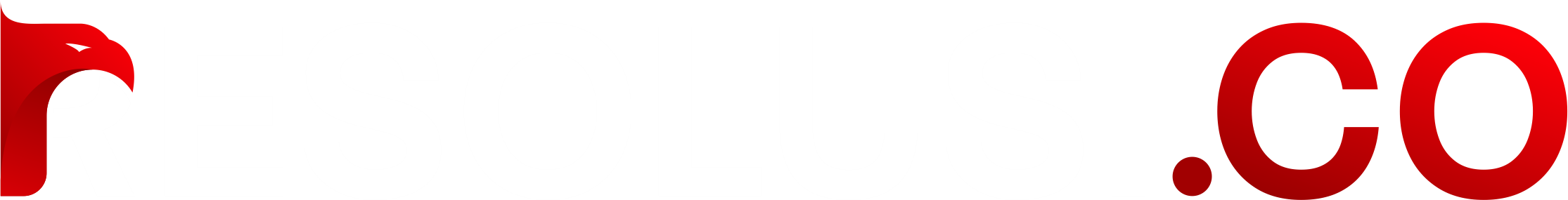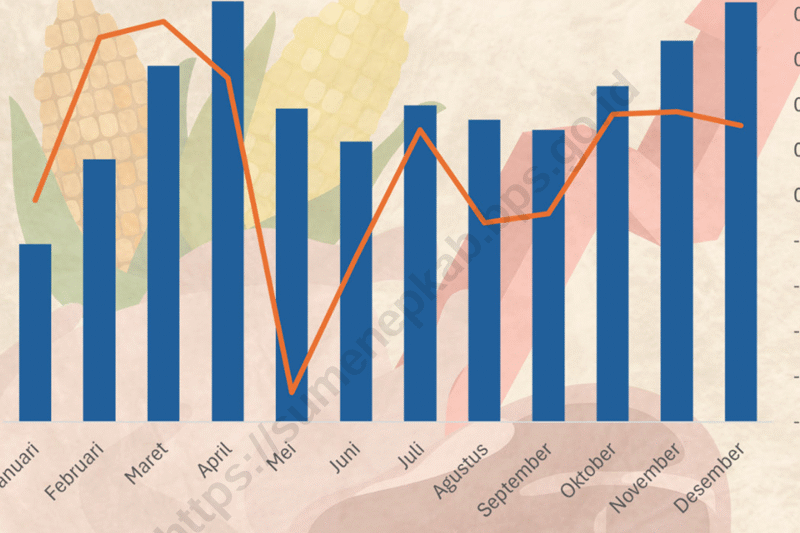Angka Bisa Menipu: Curhatan untuk Gubernur Khofifah

- Pertumbuhan ekonomi 1,70% yang dirayakan menyembunyikan defisit APBD yang melonjak 2,5 kali lipat (dari Rp1,77 T menjadi Rp4,39 T). SiLPA yang membengkak menunjukkan perencanaan buruk atau eksekusi program yang lemah.
- Ekonomi Jawa Timur terpecah: wilayah utara (Surabaya-Gresik-Sidoarjo) menyumbang 50% PDRB, selatan hanya 20%. Kesenjangan upah mencapai 2x lipat (Surabaya Rp5 juta vs Situbondo Rp2,3 juta). Pertumbuhan tidak merata, hanya memperkaya yang sudah kaya.
- Penurunan pengangguran dan kemiskinan (secara agregat) menyembunyikan fakta: 63,91% pekerja di sektor informal tanpa jaminan, lulusan SMK/universitas justru lebih banyak menganggur (5,87% dan 5,60%), dan 3,8 juta orang miskin masih menghabiskan 9% pendapatannya untuk rokok sebagai pelarian.
 , Pada jam pagi, sekira pukul delapan seperempat, beranda berita dipenuhi wajah Gubernur Jawa Timur. Di belakangnya, proyektor menampilkan grafik yang menaik: 1,70 persen. Judul berita beragam, tetapi andai disarikan, mungkin berbunyi: pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga tertinggi se-Pulau Jawa. Kamera mengambil sudut terbaik. Seseorang tampak menunjuk angka itu dengan pose bangga.
, Pada jam pagi, sekira pukul delapan seperempat, beranda berita dipenuhi wajah Gubernur Jawa Timur. Di belakangnya, proyektor menampilkan grafik yang menaik: 1,70 persen. Judul berita beragam, tetapi andai disarikan, mungkin berbunyi: pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga tertinggi se-Pulau Jawa. Kamera mengambil sudut terbaik. Seseorang tampak menunjuk angka itu dengan pose bangga.
Saya membuka laptop. Mencari berita dan dokumen afirmasi. Bukan tidak percaya, tetapi dalam benak saya, angka tak bisa ditelan mentah begitu saja. Angka bisa saja menipu.
Betul saja. Menurut saya, APBD Jawa Timur 2025 menampakkan luka yang coba disembunyikan di balik narasi megah. Defisit melonjak dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun, naik 2,5 kali lipat. Belanja membengkak Rp2,71 triliun. Pendapatan? Merangkak naik Rp91 miliar saja.
Ini bukan cuma soal angka di spreadsheet. Tetapi ia terejawantah menjadi kenyataan yang sulit dibantah: berapa banyak rumah tangga di Jawa Timur yang hidup dari kartu kredit? Ini juga soal pemerintah yang menambal lubang dengan uang sisa tahun lalu, SiLPA namanya, yang melonjak dari Rp1,78 triliun menjadi Rp4,70 triliun.
Tak perlu akademisi dan ekonom untuk menerawang angka itu. Sebagai awam, mari kita gunakan seperdelapan kemampuan berpikir kita: andai memang kinerja pemerintah Jawa Timur bagus, mengapa uang tahun lalu tersisa begitu banyak? Ada dua probability dari pertanyaan di atas. Pertama, karena perencanaan amburadul, sehingga uang dianggarkan tapi tak terpakai; atau kedua, program-program berjalan setengah hati. Niat ada, tapi eksekusi loyo.
Entah kemungkinan yang mana, keduanya bukan pertanda sehat. Samasekali. Anggaran hanya bergulir seperti roda hamster: berputar kencang, tapi tetap di tempat, tak kemana-mana.
Coba kita lihat Jawa Timur dari peta, dari atlas. Di atas kertas, ia satu provinsi. Tetapi jika Anda zoom in, ia tampak seperti dua negara berbeda. Ambil garis khayal dari Surabaya ke timur, misalnya. Di atas garis itu, setengah ekonomi Jawa Timur bergeliat. Lima puluh persen PDRB berasal dari sana: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan. Pabrik-pabrik berdiri. Mall berkembang. Uang berputar cepat.
Di bawah garis, di selatannya, hanya 20 persen. Mungkin yang lazim kita lihat adalah sawah, kebun, pelabuhan kecil, dan jalan berlubang. Ini bukan qadha-qadhar geografis. Ini hasil dari pilihan elit pengambil kebijakan bertahun-tahun: jalan tol dibangun pelabuhan diperluas, ke mana investor diarahkan. Modal mengalir ke tempat yang sudah basah. Yang kering, dibiarkan mengering, mungkin sengaja diabaikan jadi tandus.
Sederhana saja. Kita lacak fakta di atas dari besaran upah minimum. Surabaya sekira Rp5.023.635 per bulan, Situbondo sekira Rp2.335.209. Kesenjangan dua kali lipat. Bukan karena orang Surabaya bekerja dua kali lebih keras, tapi karena mereka lahir di geografi yang tepat.
Lalu pertanyaan trivial yang tidak pernah dijawab dalam konferensi pers: apakah pertumbuhan 1,70 persen itu merata? Atau ia hanya membuat kaya sebagian kecil orang yang sudah kaya, memperlebar jurang yang sudah menganga?
Saya mencoba mencari data pertumbuhan per kabupaten. Sulit. Pemerintah provinsi lebih suka bicara agregat. Angka besar. Angka yang terdengar impresif. Tapi ketika dipecah ke tingkat kabupaten, ceritanya lain.
Bappeda pernah mengakui dalam sebuah konferensi: kesenjangan utara-selatan masih jadi “tantangan besar.” Loh, itu bukan saja tantangan. Kalau setengah provinsi masih tertinggal, ya, itu masalah. Masalah gede. Tapi yang mereka sebut “tantangan,” orang di selatan menyebutnya “kehidupan sehari-hari.”
Jumlah orang miskin di Jawa Timur, per Maret 2025, sebanyak 3.836.520. Turun 17.940 jiwa dari September 2024. Pemerintah merayakannya. Tapi coba bayangkan: 3,8 juta orang. Hampir sepuluh persen dari total populasi. Jika mereka berkumpul, mereka bisa mengisi Surabaya dua kali lipat.
Mereka tidak tersebar merata. Mereka menumpuk di kantong-kantong tertentu: Madura, Malang, Ponorogo, Situbondo, Bondowoso, Jember. Tempat-tempat yang jarang dikunjungi Gubernur saat panen raya. Tempat-tempat yang tidak pernah jadi latar belakang foto konferensi pers.
Saya menemukan data BPS yang menarik tapi menyedihkan. Penyumbang terbesar kedua garis kemiskinan, setelah beras, adalah rokok kretek filter. Di perkotaan: 9,61 persen dari pengeluaran orang miskin. Di pedesaan: 8,76 persen.
Bayangkan, orang yang penghasilannya Rp500.000 per bulan, setengah juta rupiah untuk makan, sewa, listrik, transport, dan segalanya, masih menyisihkan hampir sepuluh persen untuk rokok. Bukan untuk protein. Bukan untuk vitamin anak. Untuk sesuatu yang dibakar, dihisap, lalu lenyap jadi asap.
Ini bukan sekadar soal pilihan konsumen. Ini alarm tentang kehidupan yang begitu sempit pilihannya, begitu minim harapannya, hingga pelarian menjadi kebutuhan. Setelah merenung lumayan panjang, saya anggap preferensi masyarakat membeli rokok itu wajar. Bagi mereka, kadang juga bagi saya, rokok jadi obat penenang yang murah.
Jagongan mbek konco di warung-warung desa memang jadi panawar penat, sambil mendengarkan kabar tentang beberapa orang kaya lokal yang mborong mobil miliaran. Pemerintah? Mereka, katanya, sedang sibuk merayakan penurunan kemiskinan 0,29 persen.
Kabar lain di Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,88 persen pada Agustus 2025 lalu. Penurunan tertinggi di Pulau Jawa, kata pemerintah. Kabar baik. Pamflet-pamflet dibuat. Desain-desain dipajang. Tentu, kita semua butuh kabar baik.
Tapi tunggu. Saya buka data BPS lebih dalam, lebih teliti. Saya menemukan kenyatahan pahit yang membuat saya agak emosional: yang menganggur justru mereka yang terdidik. Lulusan SMK 5,87 persen, ulusan universitas 5,60 persen. Ironi yang sempurna: kita menyuruh anak-anak sekolah tinggi-tinggi, lalu mereka lulus dan tidak punya tempat kerja.
Sementara itu, 63,91 persen pekerja di Jawa Timur berada di sektor informal. Pedagang kaki lima, ojek, kang parkir, buruh lepas. Pekerjaan tanpa kontrak, tanpa jaminan kesehatan, tanpa pensiun. Hari ini kerja, besok mungkin tidak. Lalu pemerintah menyebut “pertumbuhan inklusif”?. Aduh!
Pada Mei 2025 lalu, ada sekira 481 kasus PHK dalam sebulan. Pemerintah bilang, “Ini lebih rendah dari tahun lalu.” Seolah itu penghiburan. Seolah 481 keluarga yang kehilangan penghasilan itu angka yang bisa diabaikan. Seolah mereka bukan manusia dengan tagihan listrik, cicilan motor, dan keluarga yang harus makan.
Bahkan, yang lebih menyakitkan, banyak dari PHK itu terjadi di sektor manufaktur. Pabrik-pabrik yang katanya jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Lalu timbul sangsi: jadi pertumbuhannya untuk siapa? Untuk pemilik pabrik yang bisa PHK pekerja sesukanya? Atau untuk pekerja yang hidupnya bergantung pada keputusan rapat direksi di Jakarta?
Saat seorang Gubernur berdiri di depan kamera dengan senyum lebar, menyebut angka 1,70 persen dengan begitu bangga, apa yang sebenarnya ia rayakan?
Pertumbuhan yang terpusat di wilayah yang sudah kaya? Defisit yang membengkak hampir tiga kali lipat? Pekerjaan informal yang mendominasi tanpa jaminan masa depan? Atau 3,8 juta orang yang masih menghabiskan uangnya untuk rokok karena tak ada lagi yang bisa menghiburnya?
Saya bukan ekonom, tapi saya mengerti, dala politik statistika, ada angka-angka yang dipilih dengan hati-hati untuk konferensi pers, sementara angka-angka lain, yang lebih jujur dan kadang lebih pahit, disembunyikan di bawah karpet.
Trik lawas dalam statistik: kau bisa memilih angka mana yang ingin kau tonjolkan. Kau bisa fokus pada yang naik, dan mengabaikan yang turun. Kau bisa merayakan penurunan kemiskinan 0,29 persen, dan melupakan fakta bahwa hampir 10 persen populasi masih miskin. Kau bisa bangga dengan pertumbuhan 1,70 persen, dan tidak menyebut defisit Rp4,39 triliun.
Memang, itu bukan kebohongan, secara teknis. Tapi juga bukan kejujuran. Jika angka pertumbuhan itu tidak mengurangi kesenjangan, tidak memperbaiki kehidupan orang miskin, tidak menciptakan pekerjaan yang layak, lalu untuk apa?
Grafik pertumbuhan mungkin naik, tapi di luar sana, di Madura, di Situbondo, di Bondowoso, dan daerah lain di Jawa Timur, kehidupan berjalan seperti biasa. Petani tetap menjual hasil panennya dengan harga yang sama. Buruh pabrik tetap takut di-PHK. Lulusan universitas tetap mengirim CV ke puluhan perusahaan tanpa balasan. Dan angka 1,70 persen itu tidak mengubah apa pun untuk mereka.
Mungkin itulah inti masalahnya: kita terlalu jatuh cinta pada angka, dan lupa pada warga yang memikul kisah pedihnya.