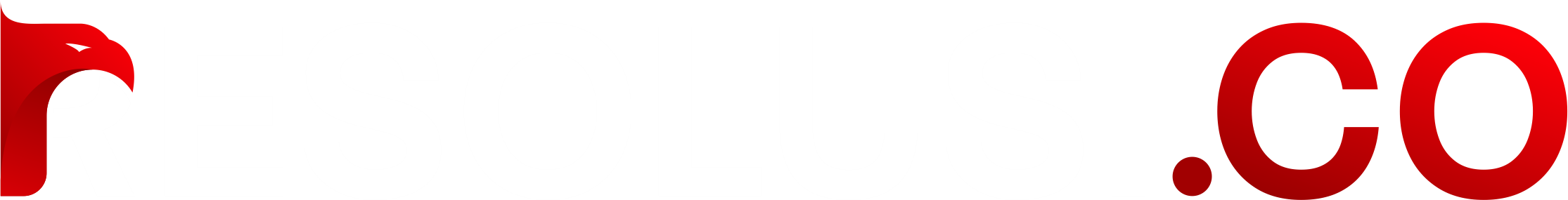Di Balik Manisnya Tapai Pordapor: Merawat Warisan di Tengah Ketidakpedulian

- Tapai singkong menjadi sumber penghidupan utama warga Pordapor, dibuat secara tradisional dan penuh ketekunan.
- Mereka menghadapi keterbatasan akses modal, pelatihan, dan dukungan pemerintah, sehingga usaha tidak berkembang.
- Warisan tapai terancam karena minimnya regenerasi dan tidak adanya penguatan pasar maupun pendampingan.
 , Pagi masih menggantung, Nyai Sa’adah sudah duduk di depan pawon dapurnya: sebuah bangunan 3 x 3 dari kayu persis di depan halaman rumahnya. Asap mengepul dari tungku tanah liat, mengaburkan wajahnya yang yang memang berusia lebih setengah abad.
, Pagi masih menggantung, Nyai Sa’adah sudah duduk di depan pawon dapurnya: sebuah bangunan 3 x 3 dari kayu persis di depan halaman rumahnya. Asap mengepul dari tungku tanah liat, mengaburkan wajahnya yang yang memang berusia lebih setengah abad.
Di sampingnya, sebuah dandang besar menjerang potongan singkong yang sudah dikupas sejak subuh untuk dibuat tapai. Memang, usai menunaikan Shubuh di langgar yang sederhana, kehidupan perlahan menggeliat di Desa Pordapor.
Nyai Sa’adah dan para tetangganya memisah jalan: sebagian menapak tanah ke ladang, sebagian lagi mengayun langkah membawa tapai ke pasar, dengan harap dan kebiasaan yang telah ditunaikannya bertahun-tahun, turun-temurun.
Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, memang bukan pusat industri. Tapi di desa kecil ini, tapai singkong bukan sekadar penganan tradisional. Ia adalah harapan, penghidupan, dan sejarah yang diwariskan turun-temurun, dari leluhur dan moyang.
“Kalau nggak buat tape, kami makan apa, Nak?” ujar Nyai Sa’adah pelan, sambil menghaluskan butir-butir ragi. “Ladang cuma cukup buat tanam padi dan jagung. Itu pun musiman. Tape ini yang bisa dijual setiap hari, untuk beli lauk setiap hari,” ucapnya.
Nyai Sa’ádah mungkin tidak berlebihan. Tetapi, di pojok desa ini, tak sedikit pemuda yang telah mengenyam pendidikan bahkan hingga tingkat master yang dibiayai dari hasil singkong. Bila mau jujur, yang harusnya pantas disebut ‘si anak singkong’ bukan hanya Chairul Tanjung, tetapi pemuda-pemudi di desa Pordapor dan sekitar yang berhasil mengenyam bangku sekolah dengan hasil tapai.
Rasa Manis yang Lahir dari Susah
Tapai singkong Pordapor punya rasa khas: sedikit asam di ujung, manis mengembang di tengah lidah, dan aroma fermentasi yang lembut. Tapi di balik manisnya, ada kisah pahit yang tak kasat mata, yang mungkin tak dialami semua orang.
Di desa ini, dan beberapa desa lain yang berdekatan, sekitar 30 rumah tangga menggantungkan hidup dari produksi tapai. Prosesnya sederhana, tetapi melelahkan: mulai dari mencari dan memanen singkong sendiri, memanennya secara manual, mengukus, meragi, hingga membungkusnya ke wadah anyaman bambu dengan daun jati. Tidak ada mesin, tidak ada pabrik. Semua dikerjakan tangan, seperti zaman nenek moyang.
Tapai singkong Pordapor ini tidak memakai pengawet. Dalam suhu kamar, masa simpannya hanya tiga sampai empat hari sebelum mulai berair dan berbau terlalu tajam. Kecuali dalam kulkas, tapai ini bisa bertahan hingga seminggu.
Tapai singkong dijual seharga Rp13.000 per kilo. Di pasar, mereka menjualnya dalam kemasan eceran kecil, dibungkus plastik. Pedagang biasa mengantar tapai ke Pasar Brumbung di Desa Brumbung, Prenduan, beberapa kadang juga ke Pasar Ganding, Pasar Lenteng, bahkan sampai ke pasar kota Sumenep menggunakan tumpangan motor atau mobil pickup warga.
Beberapa warung kecil di sekitar Prenduan dan Guluk-Guluk juga memesan tapai Pordapor ini untuk dijadikan bahan dasar gorengan. Lazimnya digoreng dengan tepung tipis dan dijual sebagai camilan murah di warung-warung pinggir jalan, sebagai pelengkap kopi. Tapi jumlahnya memang tak menentu.
“Kadang warung pesan dua kilo buat digoreng. Tapi ya harus sabar, karena bayarnya nggak selalu kontan,” kata Sutik, ibu muda penjual tapai, sambil menata kembali tapai yang sudah dingin ke dalam keranjang anyaman.
Pendapatan bersihnya sehari kadang tak lebih dari Rp150.000–Rp190.000, setelah dipotong biaya singkong, daun jati, ragi, dan ongkos ke pasar yang berjarak puluhan kilometer dari rumahnya. “Kalau sedang ramai, bisa untung lebih. Tapi sering juga rugi kalau pas hujan atau nggak ada pembeli,” ucapnya pelan.
Masalah utama mereka bukan di produksi, tapi di akses, hal ihwal yang tak pernah dihirau dan diberikan oleh pemerintah setempat. Akses modal, pelatihan, dan bantuan pemerintah.
Dapur yang Tak Dilirik, Janji yang Tak Singgah
Masalah utama para pembuat tapai di Pordapor bukan terletak pada produksi. Mereka sudah menguasai ilmu membuat tapai dari ladang hingga daun pembungkusnya. Yang tidak mereka miliki adalah akses—bukan hanya pada pasar, tapi juga pada dukungan struktural yang seharusnya datang dari pemerintah.
Akses modal, misalnya, masih menjadi kemewahan yang jauh dari jangkauan. Mayoritas dari mereka tak punya rekening bank, tak punya jaminan formal, apalagi tahu cara mengakses program Kredit Usaha Rakyat.
Beberapa dari mereka memang pernah ditawari bantuan modal dari koperasi lokal, tapi bunganya mencekik. “Kalau rugi, bisa ditagih tiap minggu. Sementara jualan tapai kan kadang untung, kadang juga enggak,” kata Sutik.
Pelatihan juga nyaris tak pernah menyentuh desa ini. Dinas terkait jarang sekali mengadakan pendampingan ke desa-desa pelosok seperti Pordapor. Pernah ada kabar akan ada pelatihan pengemasan dan digital marketing, tapi hanya berhenti sebagai selebaran di balai desa. Tidak pernah ada kelanjutannya.
Bahrul, pemuda lokal yang sempat mengusulkan label dagang dan penjualan daring, mengaku kesusahan untuk mendaptkan akses dan bantuan dari pemerintah.
“Harusnya ada pendamping yang bantu sampai produk kami punya merk, punya izin, dan bisa masuk toko oleh-oleh,” ujarnya. “Tapi sampai sekarang, ya semua diurus sendiri, sebisanya.”
Pemerintah kabupaten, yang seharusnya menjadi tulang punggung pengembangan UMKM daerah, justru nyaris absen. Tidak ada program berkelanjutan, tidak ada peta jalan pengembangan usaha rakyat desa, tidak ada perhatian untuk menjadikan potensi lokal sebagai kekuatan identitas daerah.
Padahal, tapai Pordapor punya keunikan rasa dan karakter fermentasi yang khas. Proses pembuatannya masih tradisional, dengan varietas singkong lokal dan ragi butir yang dihaluskan sendiri, tanpa pengawet dan pemanis buatan—ciri yang bisa jadi nilai jual tinggi jika dikembangkan dengan benar.
“Coba saja ada yang bantu dari kabupaten. Kami yakin, tapai di sini bisa bersaing dengan tapai Bondowoso,” kata Nyai Sa’adah.
Perbandingan itu bukan tanpa alasan. Tapai Bondowoso sudah jadi oleh-oleh nasional, didukung oleh branding kuat, kemasan modern, dan akses distribusi yang luas. Sementara tapai Pordapor masih dijual eceran di pasar desa, dibungkus daun jati, dan hilang dalam sehari jika tak laku.
“Bayangkan jika tapai Pordapor dikemas profesional, masuk ke toko oleh-oleh, ditawarkan lewat platform digital, bahkan diangkat dalam festival kuliner Madura. Ia bisa menjadi ikon baru Kabupaten Sumenep, pembeda yang tidak hanya membanggakan, tapi juga menghidupi,” treang Bahrul.
Namun sejauh ini, mimpi itu belum punya tangan untuk meraihnya. Bila berkunjung ke “desa tapai” ini, panorama yang terlihat hanyalah ketekunan ibu-ibu desa, kerja diam-diam anak muda, dan harapan yang bertahan dari satu musim panen ke musim berikutnya. Tapai Pordapor tetap dibuat setiap hari—bukan karena ia laku keras, tapi karena ia satu-satunya jalan bertahan bahkan sekadar untuk membeli beras.
Menjaga Warisan, Menantang Zaman
Di dapur-dapur desa yang berjelaga, tapai masih dibuat seperti dulu: dengan sabar, dengan tangan, dengan keyakinan bahwa rasa yang tumbuh dari peluh tak akan pernah kalah dari pabrik. Tapi mereka tahu, ini bukan usaha untuk jadi kaya—ini adalah cara bertahan hidup dengan sisa-sisa yang diwariskan para leluhur.
Meskipun susah, para perempuan di Pordapor tetap mengerjakan tapai dengan dedikasi yang nyaris ritualistik. Ada waktu-waktu tertentu untuk mencuci singkong, aturan jumlah ragi, bahkan cara menata tapai agar tidak saling bersentuhan saat fermentasi.
“Tidak semua orang bisa membuat tapai. Tekniknya mungkin sederhana, tetapi membuat tapai harus juga dibarengai dengan jiwa, emosi,” kata Nyai Sa’adah.
Tiap lembar daun jati yang dipakai membungkus tapai dipilih dengan hati-hati. Terlalu muda, maka cepat layu. Terlalu tua, maka kaku dan mudah robek. Tidak ada satu pun proses yang bisa dikerjakan sembarangan.
Nyai Sa’adah, Sutik, dan ibu-ibu lainnya tak pernah punya mimpi besar untuk membuka pabrik atau menjadi brand nasional. Mereka hanya ingin tapai mereka laku di pasar, cukup untuk membeli beras, uang jajan anak, dan ongkos ke ladang. Di tengah gempuran zaman yang menuntut serba cepat dan efisien, mereka masih memeras kesabaran untuk mengulangi proses ‘konvensional’ yang sama setiap hari.
Sayangnya, mereka menjaga warisan itu sendirian. Tak ada pendampingan dari pemerintah daerah, tak ada koperasi aktif yang membina, tak ada skema pelatihan yang berkelanjutan.
Apa yang mereka tahu hari ini, adalah hasil dari apa yang diturunkan dari nenekmoyangnya dulu. Tidak bertambah, tidak berkembang. Stagnan dalam tradisi yang agung, tapi kesepian.
Di sisi lain, dunia bergerak cepat. Penjual makanan di kota sudah bicara soal branding, storytelling produk, dan reseller daring. Tapai Pordapor masih terbungkus daun jati, tanpa label, tanpa barcode, tanpa jaminan akan laku esok pagi. Tapai ini seperti jimat lama yang terlupa dalam laci sejarah. Ia bernilai, tapi nyaris tak dikenali.
Dan ironisnya, generasi penerus pun mulai menoleh ke arah lain. Anak-anak muda Pordapor dan desa sekitarnya lebih memilih kerja di toko kota, menjadi sopir ojek daring, atau merantau ke Surabaya dan Jakarta. Tak banyak yang tertarik mewarisi pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu, tetapi sedikit hasil.
Warisan tapai ini mulai kehilangan penjaganya. Padahal, jika ada tangan yang membimbing, tapai ini bisa jadi ikon lokal yang membanggakan. Bisa saja ia menjadi simbol dari kemandirian desa, dari kekayaan rasa yang lahir dari tradisi. Tapi hingga hari ini, warisan itu dijaga oleh para perempuan tua yang terlihat lelah, dan makin sendiri.
Di antara gumpalan uap dari singkong yang dikukus, kita melihat tapai bukan hanya panganan, tapi sebuah perlawanan yang sunyi. Tapai ini menantang zaman dengan diam. Ia tidak berubah, tapi juga tidak menyerah. Dan selama itu survive, barangkali desa ini masih punya napas untuk bertahan.
Di sela kesederhanaan dan keterbatasan, tapai Pordapor menyimpan kekayaan: bukan hanya rasa, tapi juga ketekunan, sejarah, dan harapan. Desa ini mungkin kecil di peta, tapi besar dalam pelajaran tentang kemandirian dan kesabaran.
Satu per satu, singkong dikukus dan dibungkus. Disusun dalam wadah rotan, dijaga hingga tiga hari ke depan. Tanpa label, tanpa barcode, tapi penuh cinta.
Tapai ini mungkin belum masuk toko modern, tapi ia masuk ke hati mereka yang tahu: di balik rasa manis, ada kisah panjang tentang ketabahan.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: